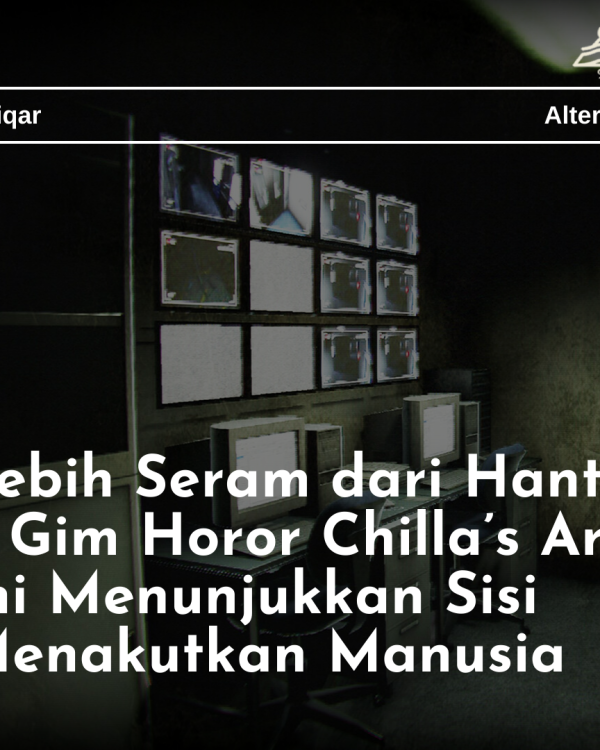Sebuah film sering kali dianggap sebagai suatu eksplorasi imajinatif sang penulis ataupun sutradaranya belaka. Namun, terkadang lupa bahwa imajinasi muncul karena terinspirasi dari peristiwa nyata. hal ini menjadikan sebuah film tidak hanya untuk tontonan belaka, tetapi juga sebagai cermin teguran atas apa yang mungkin terjadi. Begitu pula dengan dua film garapan Galder Gaztelu-Urrutia — seorang sutradara berkebangsaan Spanyol — yang berjudul The Platform (2019) dan presekuelnya The Platform 2 (2024). Melalui keduanya, penonton seakan diajak untuk menyadari bahwa terkadang fiksi hanya selangkah jauhnya dari kenyataan yang menunggu di depan mata.
Dalam dunia dan sistem yang dibangun film ini, manusia ditempatkan di sebuah menara vertikal yang kurang lebih berjumlah 333 tingkat. Di setiap tingkatnya ada sebuah ruangan dengan lubang besar di tengahnya, yang dikenal sebagai “The Pit” yakni jalur distribusi makanan bagi mereka. Setiap harinya makanan akan diturunkan ke setiap tingkat secara berurutan dan tentunya dengan waktu makan yang singkat. Hadirnya sistem ini menciptakan gambaran ketimpangan yang begitu jelas sehingga terbentuklah dua kelompok, yaitu Kaum Loyalis dan Kaum Barbarian yang selalu bersitegang sampai akhir film.
Bermula dari sistem distribusi makanan hingga konflik antarkelompok, merefleksikan ketimpangan dan perilaku manusia ketika dihadapkan pada dorongan untuk bertahan hidup. Gambaran distopia inilah yang menjadi titik awal The Platform dan The Platform 2 dalam menyampaikan kritik sosial terhadap sistem dan sisi primitif manusia. Kedua film ini menyisakan ruang tafsir bagi penonton untuk melihat ulang batas antara moralitas dan naluri bertahan hidup. Jika dilihat lebih dari sekadar tontonan, keduanya memotret kemungkinan yang tidak sepenuhnya asing dari realitas yang ada.
Simbolisme “The Pit” sebagai Cerminan Struktur Sosial
Pada film yang bergenre horor-thriller ini, “The Pit” diibaratkan sebagai eksekutor sistem yang sekaligus simbol dari struktur sosial. Diperlihatkan dari ruang-ruang vertikal yang membagi manusia dalam struktur sosial berbeda, seakan memberi ruang lebih untuk mereka yang berada di atas dan yang di bawah hanyalah menunggu kedermawanan.
“Ibaratnya kita di dunia ini punya sumber daya, tapi sumber daya dunia itu nggak dibagikan secara adil gitu ke orang-orang. Jadi di atas dapetnya yang enak dan baru nanti makin ke bawah malah dapetnya sisaan gitu-gitu,” ujar Najlaa, selaku ketua UKMF Satu Layar UPI yang melihat bahwa struktur tersebut sebagai metafora atas pembagian yang timpang.
Sejalan dengan ini, Jessica yang sudah menonton film-film ini menyampaikan nada yang sama terkait simbolisme “The Pit”.
”The pit bisa dimaknai dengan gambaran struktur sosial di Indonesia di mana akses terhadap sumber daya ditentukan oleh status sosial. Kondisi yang terjadi di penjara vertikal tersebut bisa ditafsirkan sebagai para global elit yang berada di pemerintahan cenderung menikmati sebuah kemewahan dan tidak memikirkan dan mengabaikan para rakyat yang masih sengsara di bawah,” tuturnya dalam menanggapi “The Pit” jika dimaknai langsung pada kondisi sosial Indonesia.
Sistem dalam film ini tidak secara langsung memaksa orang menjadi serakah, melainkan membuka peluang bagi sifat primitif itu muncul. Mekanisme tersebut dirancang agar penciptanya tampak bukan dalang ketidakadilan, padahal justru alat kontrol yang halus namun efektif. Gambaran ini terasa dekat dengan Indonesia, yang meski bukan menara vertikal, tetap memiliki struktur sosial kompleks: mereka yang lahir mapan lebih mudah bertahan, sedangkan yang lain berjuang hanya untuk hidup. Dengan demikian, The Pit bukan sekadar fiksi, melainkan cermin nyata dari realitas di sekitar kita.
Ketimpangan yang Dinormalisasi
Salah satu hal yang terasa paling mengganggu dari film ini adalah bagaimana ketimpangan tidak hanya terjadi, tetapi diterima oleh sebagian kelompok. Kelompok ini adalah mereka yang tidak peduli pada aturan dan hanya fokus dengan kelangsungan hidup mereka sendiri atau yang disebut Kaum Barbarian dalam film ini. Mereka merasa bahwa orang-orang yang di atas berhak mendapat lebih karena mereka sedang berada di atas. Padahal, mereka melupakan satu aturan penting dalam sistem ini: posisi dapat berganti kapan saja.
Dalam film ini, terdapat satu aturan sistem yakni posisi orang akan berubah setiap bulan. Namun, meski pernah berada di bawah, mereka yang kini di atas tetap melakukan hal yang sama. Memperlihatkan bagaimana ketimpangan bukan hanya persoalan struktur, tapi juga cara pikir yang perlahan dinormalisasi. Najlaa menyoroti bahwa ketidaksetaraan itu terjadi karena sistem yang ”struktural dan dibuat untuk mempertahankan privilege mereka yang di atas.”
Jessica menambahkan bahwa akar dari ketimpangan dalam film ini tidak hanya terletak pada perilaku para penghuninya, melainkan pada sistem yang sejak awal dirancang dengan celah ketidakadilan yang kemudian melahirkan pola pikir menormalisasi perebutan sumber daya tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi yang lain. Ia menilai bahwa di baliknya ada individu-individu yang membiarkan mekanisme ini terus berjalan, seolah mempertahankan keadaan demi keuntungan mereka sendiri.
Ketimpangan yang dibiarkan tumbuh melalui sistem dan pola pikir ini pada akhirnya menciptakan siklus yang sulit diputus. Film ini tidak hanya menyuguhkan gambaran ketidakadilan, tetapi juga mengajak untuk memahami bagaimana ketidakadilan bisa mengakar ketika kekuasaan dan kepentingan berpadu dalam satu sistem. Pesan ini membuatnya tidak hanya relevan dengan realitas, tetapi juga menjadi kritik tajam terhadap cara kerja struktur yang membentuk perilaku manusia.
Baca Juga: Ojol Korban Brutalisme Aparat: Hukum Melindungi Siapa?
Konflik Vertikal dan Horizontal
Di dalam menara tempat para tokoh tinggal, konflik tidak hanya terjadi dari atas ke bawah. Ia juga terjadi antar penghuni yang tinggal di lantai yang sama. Ketika makanan sudah tidak tersisa, rasa saling curiga muncul. Ketika sistem membuat semua orang merasa terancam, siapa pun bisa jadi musuh dalam insting pertahanan hidup manusia.
Menanggapi hal ini, Alya mengatakan, “tindakan mereka tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat sepenuhnya disalahkan karena semua ini dimulai dari yang membuat sistem tidak transparan. Jadi mereka yang ada di dalamnya melakukan hal-hal itu, semua dilandasi dari apa yang kita gak tahu dan kenapa kondisinya bisa begitu, ” ucapnya.
Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, muncul dua kelompok besar di antara para penghuni, yakni Kaum Barbarian dan Kaum Loyalis. Kaum Barbarian memilih bertindak tanpa mempertimbangkan aturan, mengutamakan pemenuhan kebutuhan mereka sendiri dengan cara apa pun. Sementara itu, Kaum Loyalis berpegang pada keyakinan bahwa sistem tetap harus diikuti untuk kebaikan bersama. Perbedaan cara pandang ini sering kali memperkeruh suasana karena masing-masing kelompok memandang pihak lain sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup mereka.
Pertentangan keduanya memperlihatkan bahwa konflik dalam menara tidak hanya dipicu oleh ketimpangan vertikal antara yang di atas dan yang di bawah. Namun oleh ketidakpercayaan horizontal di antara penghuni. Sistem yang dibiarkan tidak transparan dan tidak adil berhasil memecah solidaritas. Membuat para penghuni terjebak dalam lingkaran saling mencurigai dan saling menjatuhkan. Pada akhirnya, film ini memperlihatkan bahwa perpecahan horizontal semacam ini justru memperkuat sistem karena mereka yang di dalam sibuk berkonflik alih-alih bersatu untuk memperbaikinya.
Melihat Cara Kerja Sebuah Perlawanan
Tokoh utama dalam sekuel film ini bernama Goreng, ia digambarkan tidak ingin menjadi seperti orang lain. Ia mencoba bertahan hidup tanpa merugikan yang lain sembari mulai mencari cara untuk mengubah sistem. Namun, ia sadar bahwa perubahan tidaklah mudah. Bahkan niat baik dapat berakhir buruk ketika dilakukan dalam ruang yang tidak memberi peluang bagi keadilan untuk tumbuh.
Menurut Alya, kesadaran semacam ini diibaratkan sebagai langkah awal yang akan tambah berarti jika diikuti oleh banyak orang. “Susah sih kalau cuma sebagian yang sadar dan peduli. Keseimbangan dan keadilan itu bisa dicapai kalau semua sadar. Nggak harus nunggu perubahan dari atas, coba aja solidaritas itu dimulai dari bawah,” ujarnya.
Senada dengan itu, Najlaa memaknai perlawanan sebagai sesuatu yang mungkin dilakukan, tetapi penuh risiko. “Perlawanan itu efektif, bisa mengubah sistem. Tapi pengorbanannya besar. Banyak yang harus dikorbankan. Kayak di film, mereka ngelawan, tapi banyak juga yang mati, ” jelasnya.
Jessica menambahkan bahwa akar ketimpangan kerap berasal dari sistem atau struktur yang buruk, sehingga sebuah perlawanan memerlukan solidaritas dan empati untuk mengubahnya. “Kalau terus egois dan mementingkan diri sendiri, perubahan nggak akan terjadi sampai kapan pun. Sama seperti kondisi Indonesia sekarang, kalau ada ketidaktransparanan dan ketidakadilan, dibutuhkannya solidaritas untuk melawan.”
Gambaran ini menunjukkan bahwa di balik kisah fiksi distopia, sekuel The Platform memotret peristiwa nyata dalam upaya mengubah keadaan. Perlawanan bukan sekadar aksi satu tokoh, tetapi proses kolektif yang membutuhkan kesadaran bersama. Dalam ruang yang penuh ancaman, bahkan tindakan kecil untuk saling menjaga bisa menjadi bentuk perlawanan yang berarti.
Baca Juga: Vandalisme Tidak Lahir dari Ruang Hampa, Tembok Menjadi Saksi Kecacatan Demokrasi
Refleksi dari Cermin Distopia
Melalui sekuel The Platform, mengajak untuk melihat bagaimana ketimpangan bukan hanya soal siapa yang berada di atas atau di bawah, namun bagaimana kepercayaan sesama. Jika situasi tersebut buruk, maka akan menciptakan konflik vertikal dan horizontal yang membuat solidaritas sulit terwujud. Melihat realitas yang ada, pola ini terasa akrab, ketika manusia terpecah oleh kepentingan dan rasa saling curiga.
Kaum Barbarian dan Kaum Loyalis menggambarkan dua respons terhadap sistem yang buruk. Seperti yang terlihat dalam film, perubahan tidak akan terjadi tanpa kesadaran kolektif. Kesadaran itu harus diiringi solidaritas dan keberanian untuk menolak mengikuti arus sistem yang kemungkinannya sulit diubah.
Pesan yang dibawa dalam film ini terasa relevan di luar layar. Di mana ketidakadilan kerap bertahan bukan hanya karena struktur yang timpang, tetapi juga karena sikap pasrah dan ketidakpedulian yang mengakar. Film ini mengingatkan bahwa perlawanan tidak selalu dimulai dari aksi besar, melainkan dari langkah-langkah kecil yang membangun kepercayaan, saling menjaga, dan ikut menolak memperkuat sistem yang merugikan banyak orang. Pada akhirnya, distopia hanyalah berjarak satu langkah dari realitas yang mungkin kenyataan sudah ada di sekitar kita.
Penulis: Nabilah Novel Thalib
Editor: Suci Maharani