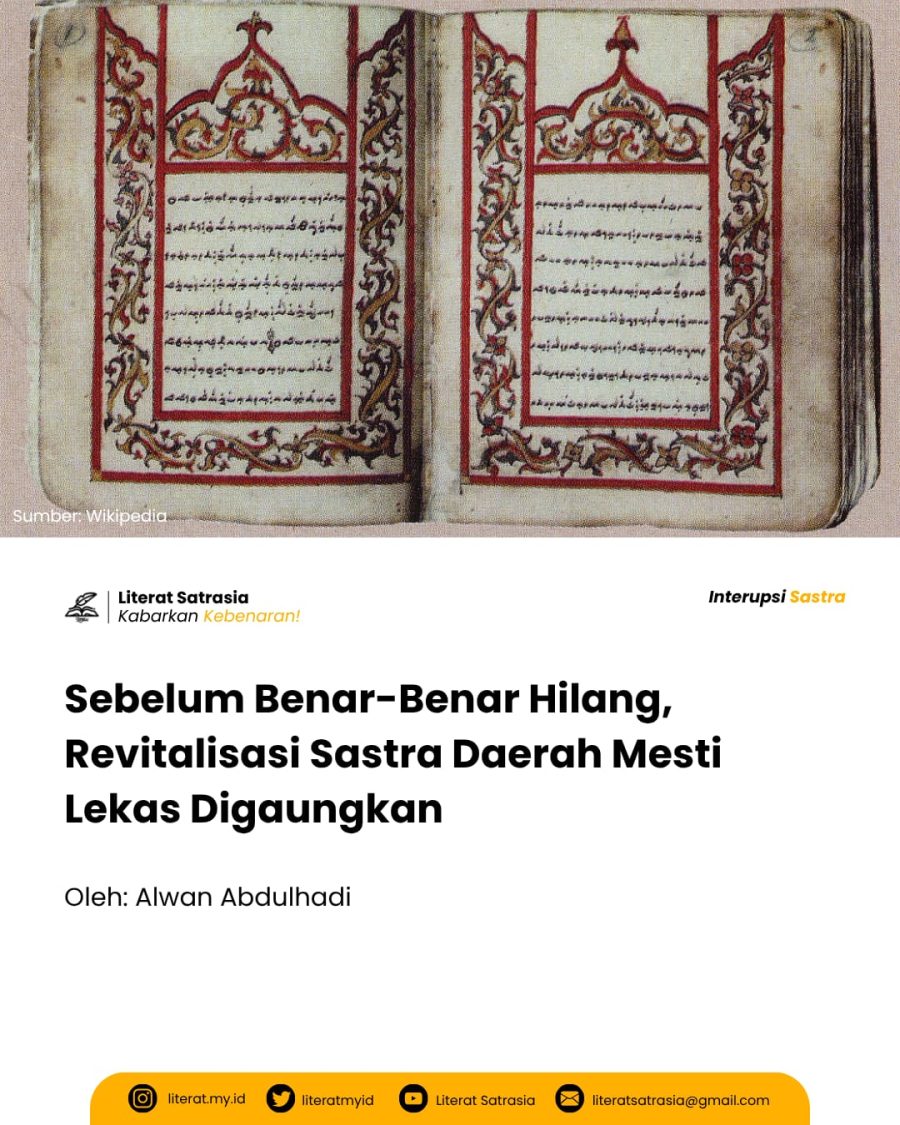Bukan Mahabharata atau Ramayana, karya sastra terpanjang di dunia ternyata berasal dari Indonesia. Judulnya La Galigo: sebuah epik mitos yang menceritakan asal mula peradaban Sulawesi Selatan, kisah cinta dan peperangan, hingga mitos-mitos penciptaan. Meski ditulis dengan aksara Bugis kuno, tak menghalangi La Galigo dalam melawan ketidakterbacaan. Pada tahun 2011, UNESCO menetapkannya sebagai Memory of The World.
Hal lain yang membuatnya istimewa terdapat pada muatan lokalitas di dalamnya. Identitas budaya Sulawesi Selatan, terutama suku Bugis, Mandar, dan Toraja berdiri tegak seperti benteng Rotterdam. Kemasyhuran itu terus diwariskan pada generasi yang datang kemudian, dan begitulah keberakaran budaya terbentuk di sana.
Zaman pun lewat, sekelebat, dan La Galigo kemudian diserap ke berbagai karya, khususnya dalam lingkup sastra. Seorang sutradara asal Texas, Robert Wilson, mengadaptasinya ke bentuk teater musikal. Demikian juga Faisal Oddang, putra daerah Sulawesi Selatan, memanfaatkan epos ini sebagai ruh dalam antologi puisinya yang berjudul Manurung: 13 Pertanyaan untuk 3 Nama. Kekayaan tafsir yang lahir dari upaya-upaya semacam itu membuat eksistensi La Galigo dapat bertahan sampai beratus tahun mendatang.
Baca Juga: Puisi “Mei: Jakarta, 1998” sebagai Ingatan dan Perlawanan – Literat
Sayangnya, kecemerlangan La Galigo hanya pengecualian dari sekian banyak sastra daerah yang tersisihkan. Sebab tak bisa dimungkiri, saat ini arus globalisasi seakan memenjarakan nilai-nilai lokal ke dalam sel isolasi. Dan sastra daerah, meski tidak bersalah, menjadi yang paling perih hukumannya: terbuang dan kehilangan arti pulang.
Di Gorontalo misalnya, nasib sastra daerah bagai sekarat hutan adat. Seiring waktu, keberadaan puisi lokal seperti Palebohu dan Tanggomo kian langka dan mungkin hanya tersisa beberapa. Jika tidak segera diselamatkan, warisan budaya itu dikhawatirkan akan menyusul Bungga dan Wulito ke jurang kepunahan.
Sastra lisan etnis Moronene di Bombana, Sulawesi Tenggara juga menghadapi persoalan serupa. Tradisi mendendangkan epik mitos berjudul Kada sudah mulai ditinggalkan di sana. Memudarnya praktik sastra lisan berimbas langsung pada karakter generasi muda setempat yang mengalami degradasi kesantunan, sebagaimana yang diamati tokoh adat dan budaya Moronene, Nurdin, S.Ag., M.Hum.
Tidak hanya di ranah sastra, ancaman kepunahan menyasar pula pada populasi bahasa daerah. UNESCO bilang, paling tidak sepuluh bahasa hilang setiap tahunnya, dan pada abad ke-21 laju kepunahan itu diprediksi lebih cepat terjadi. Ini sangat mengkhawatirkan, sebab musnahnya bahasa berarti musnah juga sastra. Dan mungkin itulah sebabnya dekade terakhir ini partisipasi generasi muda dalam tradisi bersastra menurun hingga 30%, sebagaimana data yang dicatat Kemendikbud pada tahun 2022.
Baca Juga: Kafka on the Shore: Menyelami Realisme Ajaib Haruki Murakami – Literat
Alih-alih dijaga sehingga digdaya sebagai tonggak budaya, sastra daerah malah ditinggalkan begitu saja. Padahal perannya sangat sentral, yakni menyampaikan pengetahuan dan kebijaksanaan yang telah dihimpun para moyang sejak berabad-abad silam. Contoh konkretnya, selain La Galigo, terdapat juga pada tradisi Mappadendang di kalangan masyarakat Bugis. Mereka pada praktiknya akan menyanyikan pantun dan syair, bukan cuma sebagai hiburan, tetapi juga sarana memahami nilai luhur seperti kerja keras, kejujuran, dan saling menghormati.
Sebelum semuanya benar-benar hilang, upaya revitalisasi mesti lekas digaungkan. Langkah pertama mungkin dapat dimulai melalui pendidikan formal. Caranya adalah dengan memasukan materi sastra daerah ke dalam kurikulum sekolah, mulai dari jenjang dasar sampai menengah. Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan melaporkan, lebih dari 200 sekolah di sana telah melakukan revitalisasi sastra daerah dengan tujuan mengenalkan nilai budaya kepada siswa. Berkaca dari itu, upaya serupa dapat diterapkan juga di daerah lain guna meraih tujuan yang sama.
Tidak hanya secara formal, komunitas-komunitas lokal juga dapat berperan aktif dalam upaya melestarikan sastra daerah. Melalui festival sastra, misalnya mereka mengajak masyarakat setempat berkumpul, berbagai cerita, menampilkan puisi atau pantun, dan mengikat satu sama lain dengan akar budaya yang sama. Sehingga dengan sendirinya, baik generasi muda maupun tua, bisa lebih memahami dan menghargai nilai-nilai budayanya
Sebagai alternatif lain, keberadaan teknologi dapat dimanfaatkan sebagai media revitalisasi sastra daerah. Memasukan cerita rakyat, pantun, atau hikayat ke platform digital akan memperluas sekaligus mempermudah akses terhadapnya. Bentuknya tentu disesuaikan dengan zaman, bisa berupa e-book, audiobook, atau bahkan video animasi. Dengan demikian, sastra daerah bisa diakses berbagai kalangan sehingga tetap eksis di zaman yang kian berkembang.
Melestarikan sastra daerah berarti juga mewariskan kearifan pada generasi selanjutnya. Sekian.
Baca Juga: Dari Leila S. Chudori hingga Enggano: Jurnalisme dan Kebenaran Motto – Literat
Penulis: Alwan Abdulhadi
Editor: Rifa Nabila