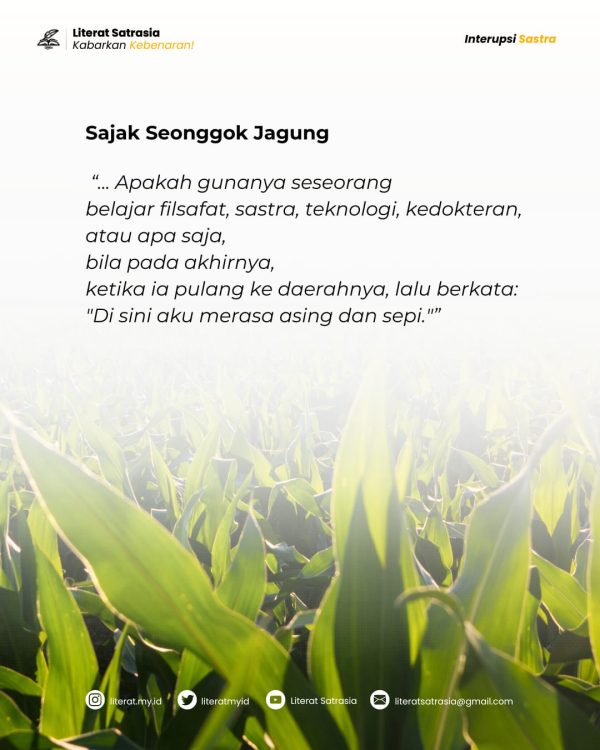Hidangan makan siangku hari ini begitu spesial. Sepotong daging rusa muda dengan saus barbeku yang mengguyur seluruh permukaan daging, ditemani acar rumput laut segar, dan dilengkapi segelas bir impor dari Jerman sebagai minumannya. Ah, tak pernah kumerasa sebahagia ini hanya karena hidangan makan siang. Apalagi setelah berada di sini, jadwal makanku jadi kurang teratur yang mengakibatkan tubuh ini mengurus. Dan kurasa menu ini akan menjadi menu favoritku untuk selama-lamanya.
Mereka memperlakukanku dengan begitu baik dalam tiga hari belakangan ini. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, diriku diperlakukan layaknya binatang. Diseret, ditelanjangi, bahkan dipukuli. Kamar penginapanku dalam tiga hari ini juga jauh lebih baik daripada hari sebelumnya yang hanya beralaskan tikar saja.
Kamar baru ini terasa lebih nyaman untuk ditempati dengan adanya bed cover empuk berwarna putih yang berada di pojok kanan kamar, sebuah kamar mandi kecil di ujung kamar bagian kiri, dan jendela yang langsung menghadap ke arah taman meskipun dihalangi jeruji. Namun, aku cukup mengapresiasi mereka karena telah melayani dengan sepenuh hati selama tiga hari ini.
Sebenarnya aku belum pernah sama sekali mencicipi daging rusa muda yang disiram saus barbeku serta ditemani acar rumput laut. Tetapi, Kepala Sipir menawarkanku satu permintaan istimewa. Kemudian dalam pikiranku terlintas daging rusa muda dengan saus barbeku dan acar rumput laut, serta sebuah bir impor untuk sekadar melengkapi hidangan spesial ini. Setidaknya aku harus berterima kasih kepada Kepala Sipir karena telah mengabulkan permintaanku.
Kepala Sipir merupakan orang yang menyambutku saat pertama kali aku menginjakkan kaki di sini. Dia menyambutku dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan membosankan, dan tanpa ada semacam tarian adat atau jamuan selamat datang. Mungkin seperti itulah tradisi penginapan di sini. Entah, aku juga tak tahu kalau itu berlaku untuk penghuni lain. Aku masih ingat pertanyaan yang selalu ia layangkan kepadaku.
“Mengapa kau bunuh gelandangan tua itu, wahai anak muda?”
Dengan ekspresi datar, ia selalu menanyakan perihal kematian gelandangan tua itu. Rasanya, ia hanya menjalankan tugasnya saja ketimbang mengasihani atau berempati terhadap gelandangan tua itu. Mungkin ia hanya peduli kepada kepala plontosnya jika ada rambut yang mulai tumbuh di kepalanya. Aku berani menjamin kalau ia selalu mengerik rambut di kepalanya tiap seminggu sekali agar kepala plontosnya tetap berkilau saat tersorot pantulan cahaya. Sungguh, kadang aku merasa terganggu oleh pantulan cahaya dari kepalanya ketika sedang menceritakan apa yang terjadi malam itu.
Aku merasa kasihan terhadap gelandangan tua itu. Tua, kurus, rapuh, lusuh, dan bahkan tak memiliki kawan berbincang. Kebetulan malam itu aku membawa makanan yang baru saja kubeli dari pasar dekat penginapanku. Namun, di tengah perjalanan menuju arah pulang, aku melihat gelandangan tua itu sedang terkapar tak berdaya. Akhirnya kuputuskan untuk memberikan makananku kepadanya. Aku pun duduk bersamanya di emperan sebuah gang sambil berbincang, dan menemani gelandangan tua itu menyantap makan malamnya.
Dia menyantapnya dengan sangat lahap. Di sela-sela perbincangan, ia mengungkapkan bahwa dirinya belum makan selama tiga hari. Seketika saja aku merasa seperti ada yang menghujam dadaku. Aku merasa sedih. Miris. Ironis.
Aku mulai berpikir bagaimana caranya aku bisa membantu mencukupi kebutuhan gelandangan tua itu, sebab aku tak mampu mencukupi kebutuhannya setiap saat. Kemudian terlintas di benakku kisah tentang surga yang dipenuhi berbagai macam makanan beserta sungai khamr yang tak pernah kering airnya.
Aku berniat mengantarkan gelandangan tua itu pergi ke surga sana agar dirinya terlepas dari jerat kesengsaraan dunia, dengan mengatakan padanya bahwa aku akan memberinya suatu hadiah, supaya mudah dipahami olehnya.
“Pak, saya ingin memberi suatu hadiah untuk bapak, tetapi bapak harus menutup mata terlebih dahulu.” Ucapku pada gelandangan tua itu.
Dengan wajah sumringah dan tenaga yang mulai pulih kembali, gelandangan tua itu menyetujui untuk ditutup matanya sesaat supaya bisa mendapatkan hadiah dariku.
Kemudian kututup matanya menggunakan kain sakuku, lalu menguji penglihatan gelandangan tua itu.
“Apa bapak masih bisa melihatnya?” tanyaku sambil mengacungkan beberapa jari ke depan wajahnya.
“Sepertinya dunia akan menjadi gelap sementara, wahai anak muda.” jawab gelandangan tua itu dengan suara paraunya.
Aku pun langsung mengambil sepotong besi berujung lancip yang berada di samping tempat sampah besar, dan tanpa meminta izin lagi langsung kutusuk gelandangan tua itu beberapa kali hingga dia tergeletak. Setelah menyelamatkan seorang gelandangan tua dari kesengsaraan dunia, Saat hendak pergi, aku ingin memastikan kembali bahwa dia benar-benar telah mati. Kuambil lagi potongan besi tadi untuk menusuk kembali tubuh gelandangan tua itu, namun sayangnya perbuatanku tertangkap basah oleh petugas sampah setempat yang langsung meneriaki diriku.
“Woi, gila. Ngapain lu!” teriakan petugas sampah itu mengejutkanku.
Dalam keadaan terpojok aku mencoba tenang dan memberi tahu maksud tujuanku kepadanya. Akan tetapi, dengan perasaan marah atau semacamnya, dia tetap meneriakiku, dan alhasil teriakannya mendatangkan kerumunan massa di gang gelap nan sempit itu.
Akhirnya aku dihakimi oleh beberapa massa, petugas sampah itu seakan menjadi pemimpin dari para massa yang mengamuk atau apalah itu. Aku diikat, dipukuli benda tumpul, diinjak, dan kebengisan lainnya yang tak bisa kusebutkan secara rinci. Tak berselang lama terdengar suara sirene mobil polisi mengiung-ngiung di tengah kericuhan kami, yang menandakan bahwa aku akan dijemputnya.
Aku berkata kepada Kepala Sipir bahwa aku merasa kasihan terhadap nasib gelandangan tua itu. Namun, Kepala Sipir tetap memutuskanku untuk menginap sesaat di tempat penginapannya sampai keputusan yang ditentukan. Aku pun menyetujuinya dengan anggukan karena terasa sulit untuk berbicara ketika wajah sedang lebam-lebamnya.
Baca juga : Hari Puisi Nasional: Momentum Mimpi Seribu Tahun Chairil Anwar
Gedoran pintu besi kamarku membuyarkan seluruh jelajah waktuku dengan sekejap. Terdengar pintu berdecit, terbuka. Lalu seseorang memanggil namaku dengan begitu tegas, dan menjelaskan maksud dari tujuannya.
“Terpidana Andrew, Kepala Sipir meminta anda untuk bersiap-siap sekarang juga.” ucap seseorang berbadan besar dengan senapan di genggaman tangannya, dan langsung menutup kepalaku menggunakan kain hitam lalu menuntun perjalanan tiba-tiba ini ke tempat yang ia tuju.
Di perjalanan gelapku —karena penglihatan tertutup oleh kain hitam apek— aku membangun kembali lamunanku yang sebelumnya dihancurkan oleh bawahan si Kepala Sipir. Aku mulai memaki dunia ini dengan seluruh kemunafikannya. Mereka semua mengadiliku dengan dalih perbuatan keji karena telah membunuh gelandangan tua itu secara kejam. Padahal, aku hanya membunuhnya dengan pasti sehingga ia dapat mati dengan cepat. Aku lebih tak tega apabila dia mati perlahan karena lapar atau kedinginan di pinggir jalan, lalu tak akan ada yang memedulikan kematiannya.
Perjalanan tiba-tiba dan gelap ini sampai lebih singkat dari yang kubayangkan. Bawahan si Kepala Sipir mendorongku dengan cukup kasar. Ah, ingin sekali aku mendengarkan lagu Bob Marley berjudul “I Shot The Sheriff”. Bawahan si Kepala Sipir menyuruhku untuk bersandar. Aku tidak tahu apa yang aku sandari saat ini, namun terasa seperti balok kayu kasar yang tidak diamplas sama sekali. Lalu, lenganku diikat mengitari bagian belakang tubuh kayu kasar yang tak diamplas ini.
Cuaca hari ini rasanya amat menyengat. Angin kering berlalu, dan membuat pikiranku menjadi kacau. Ingin sekali kukatakan pada bawahan Kepala Sipir bahwa aku ingin menenggak bir impor kembali. Tapi apa daya, mulutku juga disumpal.
Terdengar dari kejauhan orang-orang yang sedang berbincang. Mungkin sekitar lima sampai enam orang. Kemudian aku menyibukkan diri dengan bersenandung “I Shot The Sheriff” di dalam hati —karena terasa cocok dengan suasana saat ini.
i shot the sheriff
but i didn’t shoot no deputy, oh no! oh!
i shot the sheriff
but i didn’t shoot no deputy, ooh, ooh, oo-ooh.
Ketika sedang asyik bersenandung, aku mendengar ada yang berseru dengan lantang. Aku tidak tahu apa maksudnya, hanya terdengar seperti aba-aba.
“Bersiap!”
Seperti itulah suaranya, lalu diiringi oleh kokangan senapan setelahnya.
“Satu,”
Aku mulai kesal dengan suara itu.
“Dua,”
“Tiga!”
Di hitungan ketiga, terdengar suara letusan senapan, “DORRR!” dan pada saat itu juga aku berubah pikiran. Sepertinya lebih baik menyenandungkan lagu Led Zeppelin berjudul “Stairway to Heaven” di detik-detik terakhir ini.
Penulis: Rifan Muhammad
Editor: Afifah Dwi Mufidah
Baca juga : Hari Puisi Nasional: Momentum Mimpi Seribu Tahun Chairil Anwar