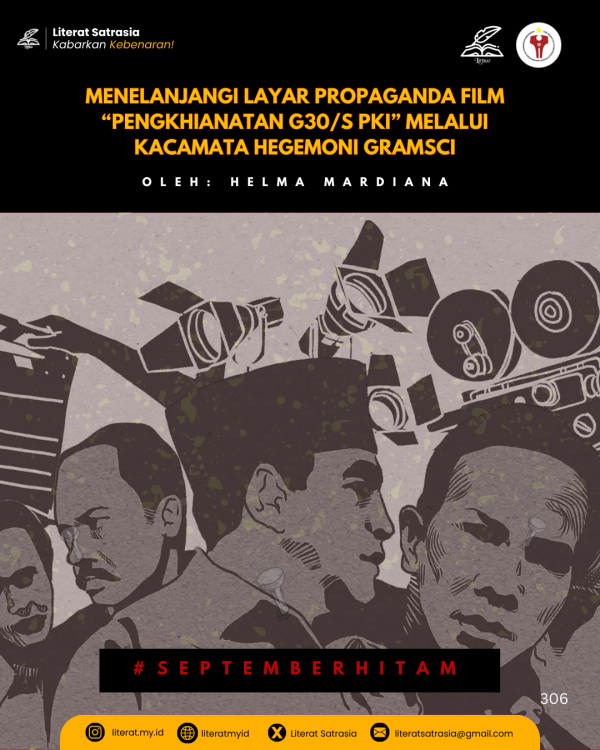Reformasi 1998 menjadi titik balik terbesar dalam sejarah politik Indonesia. Ketika itu, rakyat menuntut enam agenda dasar yang kelak dijadikan rujukan arah bangsa: mengadili Soeharto dan kroninya, membatasi masa jabatan presiden, menghapus dwifungsi ABRI, menegakkan supremasi hukum dan HAM, melaksanakan otonomi daerah, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih. Agenda-agenda ini bukan sekadar tuntutan teknis, melainkan kontrak sosial yang menegaskan bahwa kekuasaan harus berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir elite.
Namun, perjalanan pasca-Soeharto menunjukkan realitas pahit. Reformasi yang semestinya menata ulang negara justru melahirkan demokrasi yang hanya bersifat prosedural. Pemilu memang rutin digelar, tetapi keputusan strategis tetap dikendalikan pemilik modal politik dan ekonomi. Elite lama bertransformasi, masuk ke sistem demokrasi baru, lalu memanfaatkan celah prosedur untuk melanggengkan kekuasaan. Reformasi yang semula diharapkan untuk menjadi pintu pembaruan pun justru menjadi panggung kompromi antara wajah lama dan wajah baru yang sejatinya tidak pernah berbeda.
Lahirnya Gelombang #ReformasiDikorupsi
Kekecewaan rakyat terhadap mandeknya reformasi memuncak pada September 2019. Saat itu, DPR dan pemerintah tergesa-gesa mengesahkan Revisi Undang-Undang KPK meski penolakan publik sangat besar. Tidak berhenti di situ, RKUHP digulirkan dengan memuat pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil. Situasi ini menyalakan bara protes di banyak kota. Mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil turun ke jalan dengan membawa satu seruan lantang: jangan biarkan reformasi dikorupsi.
Tagar #ReformasiDikorupsi segera menjelma dan menjadi simbol perlawanan baru. Gelombang demonstrasi menuntut tujuh poin utama: pembatalan RKUHP dan rancangan undang-undang bermasalah lainnya; penerbitan Perppu KPK; pengesahan RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; hingga penghentian kriminalisasi aktivis, militerisasi Papua, dan pelanggaran HAM. Tuntutan ini bukan sekadar daftar keinginan, melainkan wujud kekecewaan kolektif terhadap arah negara yang kian menjauh dari janji Reformasi 1998.
Namun, yang terjadi di jalanan justru brutalitas aparat. Beberapa orang meninggal dunia, puluhan luka, dan ratusan ditangkap. Rekaman pemukulan, tendangan, dan penggunaan benda tumpul oleh aparat beredar luas. Negara menjawab kritik rakyat bukan dengan dialog, melainkan gas air mata dan pentungan. Peristiwa ini membuktikan bahwa budaya represif yang melekat pada Orde Baru masih tetap hidup di era yang mengaku demokratis.
Oligarki Lama dengan Wajah Baru
Jika dicermati, wajah Orde Baru memang tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti kostum. Ada tiga jalur utama transformasi yang menegaskan hal ini. Pertama, jalur politik elektoral. Figur lama, mulai dari jenderal hingga birokrat era Orde Baru, muncul kembali di panggung politik dengan legitimasi baru. Prabowo Subianto, yang dulu jenderal Orde Baru, kini menjabat Presiden RI 2024-2029. Luhut Binsar Pandjaitan masih berperan penting dalam kabinet. Partai Golkar, warisan politik Soeharto, tetap eksis sebagai kekuatan parlemen.
Kedua, jalur ekonomi. Konglomerat lama masih menguasai sektor-sektor strategis. Grup Salim mendominasi pangan; Sinar Mas merajai pulp, kertas, dan properti; sementara Astra berkuasa di otomotif. Oligarki ekonomi yang tumbuh di masa Orde Baru tidak pernah benar-benar tumbang. Reformasi justru memberi mereka ruang baru untuk memperluas pengaruh.
Ketiga, jalur budaya birokrasi represif. Tanggapan negara terhadap kritik rakyat pada 2019 membuktikan bahwa aparat masih memelihara pola lama. Kekerasan terhadap demonstran, pembiaran atas pelanggaran HAM, serta kriminalisasi aktivis dan jurnalis adalah warisan Orde Baru yang terus dibawa ke era demokrasi. Reformasi yang digadang akan menegakkan supremasi hukum justru melestarikan impunitas.
Baca Juga: Vandalisme Tidak Lahir dari Ruang Hampa, Tembok Menjadi Saksi Kecacatan Demokrasi
Enam Tahun Berlalu, Tuntutan Masih Menggantung
Kini 2025, enam tahun setelah aksi #ReformasiDikorupsi, tuntutan mahasiswa 2019 tetap relevan. RKUHP memang disahkan dengan berbagai kontroversi, Perppu KPK tidak pernah terbit, RUU PKS baru disahkan setelah perjalanan panjang dan penuh tarik-menarik, sementara pelanggaran HAM berat masih jauh dari penyelesaian. KPK sendiri kehilangan taring: lembaga yang dulu menjadi harapan kini lebih sering dipandang sebagai instrumen politik.
Ruang partisipasi publik juga semakin mengecil. Demonstrasi dibatasi, aktivis dikriminalisasi, dan media sosial diawasi. Demokrasi yang dijanjikan sebagai ruang kebebasan berpendapat justru menjadi arena penuh sensor halus. Ironisnya, semua ini berjalan di bawah jargon reformasi. Demokrasi kita lebih sering berhenti di bilik suara lima tahunan, sementara dalam keseharian rakyat tetap tersisih dari pengambilan keputusan.
Reformasi yang Dikooptasi
Benang merah perjuangan rakyat terlihat sejak Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) 1966 yang menuntut: 1) turunnya harga pangan dan BBM, 2) pembubaran PKI, dan 3) perombakan kabinet Dwikora. Semangat Tritura 1966 kala itu merefleksikan bahwa rakyat tidak akan diam ketika negara gagal menjawab kebutuhan mereka. Dari Reformasi 1998 hingga #ReformasiDikorupsi 2019 menandakan bahwa rakyat kembali bergerak ketika negara gagal. Akan tetapi, pelajaran pentingnya, reformasi bukanlah tujuan akhir. Reformasi adalah proses yang terus diuji. Ia bisa menjadi jalan pembebasan, tetapi juga bisa dikooptasi sebagai instrumen pelanggengan kuasa.
Realitas yang kita lihat hari ini lebih mendekati yang kedua. Reformasi telah menjadi mekanisme kosmetik. Wajahnya demokratis, tetapi isinya oligarkis. Rakyat digiring untuk percaya bahwa partisipasinya sudah cukup dengan mencoblos, sementara elite politik dan ekonomi tetap menentukan arah bangsa. Di sinilah letak ironi besar: reformasi yang dulu dijanjikan sebagai titik balik justru menjelma sebagai panggung sandiwara.
Reformasi Sejati Masih Harus Diperjuangkan
Enam tahun #ReformasiDikorupsi adalah pengingat keras bahwa janji reformasi belum ditepati. Jika wajah-wajah baru pemerintahan hari ini terus mengulang pola lama, rakyat harus bersiap kembali menagih. Sebab, reformasi sejati tidak akan datang dari ruang sidang DPR atau meja rapat kabinet. Reformasi sejati hanya akan hidup jika rakyat terus bersuara, turun ke jalan, dan mengawasi jalannya kekuasaan.
Sejarah menunjukkan bahwa rakyat tidak pernah benar-benar diam. Dari Tritura hingga aksi September 2019, suara rakyat selalu muncul ketika negara melupakan tugasnya. Pertanyaan pentingnya kini: apakah bangsa ini masih berani memperjuangkan reformasi sejati, atau memilih tenggelam dalam demokrasi semu yang hanya menjadi kedok bagi pelanggengan oligarki?
Baca Juga: Mengingat Kembali: 21 Tahun Kematian Munir di Balik September Hitam
Penulis: Sithah Auladah Sholihah
Editor: Laksita Gati Widadi