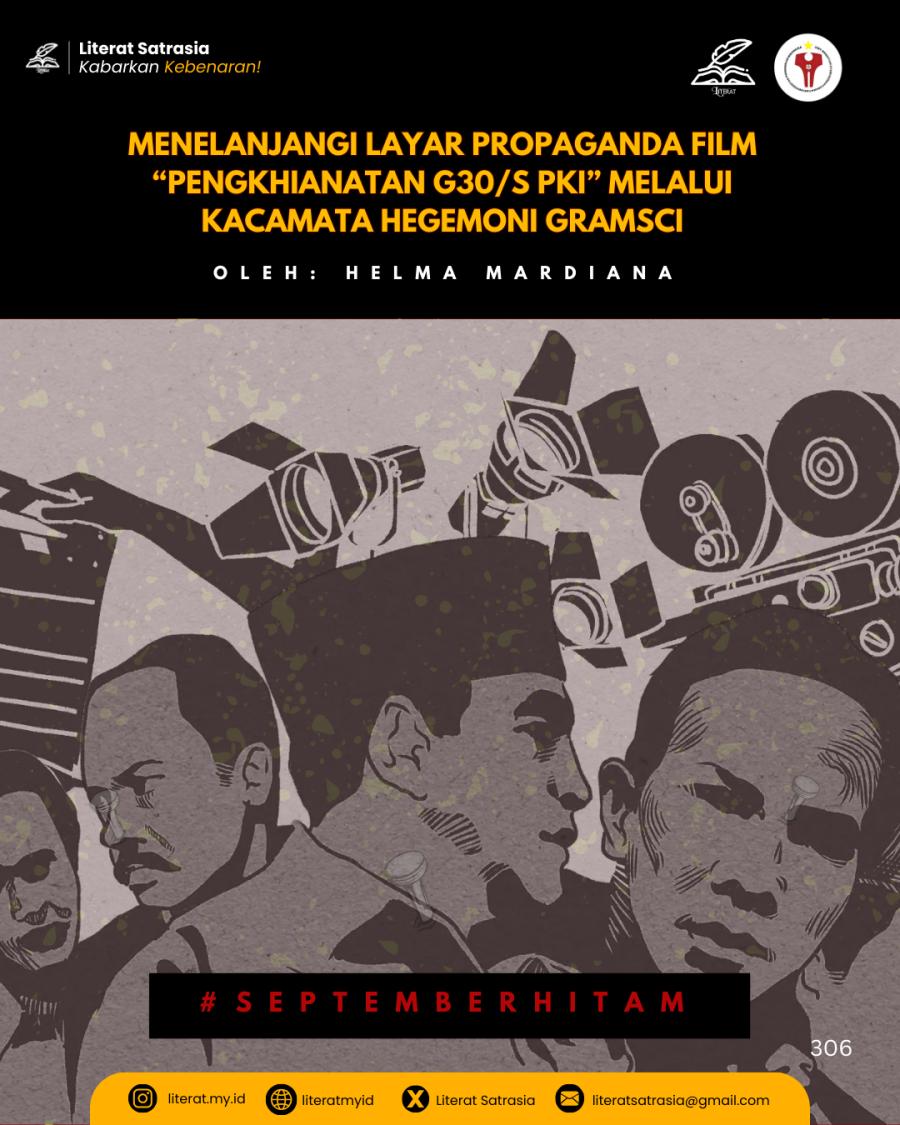Apa jadinya jika ingatan kolektif suatu bangsa dibentuk oleh sebuah film? inilah yang dialami masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Setiap tanggal 30 September pukul 10 malam, film “Pengkhianatan G30S/PKI” diputar serentak di seluruh stasiun televisi. Selama lebih dari tiga dekade, rakyat Indonesia menyaksikan, mempercayai, dan menelan mentah-mentah narasi tunggal yang disuguhkan. Narasi ini berisi bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dalang dari tragedi, sementara militer tampil sebagai pahlawan. Namun, benarkah demikian? Apakah narasi tersebut sepenuhnya mencerminkan kebenaran sejarah? Ataukah ada maksud tersembunyi di balik praktik propaganda yang dijalankan oleh rezim Orde Baru?
Praktik Hegemoni dalam Penulisan Sejarah Masa Orde Baru
Sejarah bukanlah dokumen tunggal yang selalu objektif. Ia hanyalah fragmen dari kejadian asli yang kompleks. Penulisan sejarah dapat disusupi dengan narasi yang dibuat oleh pihak berkuasa demi kepentingan mereka sendiri. Praktik semacam ini seringkali dilakukan oleh kelompok dominan untuk melanggengkan kekuasaannya dengan cara membentuk narasi tunggal agar diterima sebagai kebenaran bersama dan menciptakan kesadaran sukarela pada masyarakat. Fenomena ini nyatanya dapat dikaji melalui teori hegemoni Gramsci.
Dalam buku Selections from the Prison Notebooks, Gramsci mengungkapkan bahwa praktik mempertahankan kekuasaan tidak selalu melalui koersi atau kekerasan fisik berupa paksaan, ancaman, atau intimidasi. Cara yang lebih efektif adalah dengan melakukan konsensus atau persetujuan sukarela berupa penyebarluasan ideologi, nilai, dan pandangan tertentu pada masyarakat luas melalui lembaga pendidikan, media, dan seni. Hingga akhirnya, masyarakat umum menganggapnya sebagai sesuatu yang benar, wajar, dan masuk akal. Strategi ini terbukti berhasil diterapkan di Indonesia masa Orde Baru.
Salah satu contoh paling kuat dari fenomena hegemoni di Indonesia adalah narasi seputar peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Peristiwa ini tidak hanya dimaknai sebagai titik balik yang meruntuhkan Orde Lama dan melahirkan Orde Baru. Akan tetapi, peristiwa tersebut menjadi fondasi langgengnya kekuasaan rezim hingga lebih dari tiga dekade. Adapun alat utama yang digunakan untuk menanamkan narasi tunggal ini pada benak seluruh rakyat Indonesia adalah sebuah film.
Baca Juga: Dari ’65 hingga Affan Kurniawan 2025: Melawan dengan Merawat Ingatan
Film sebagai Alat Hegemoni rezim Orde Baru
Film berjudul “Pengkhianatan G30S/PKI” disutradarai oleh Arifin C. Noer tahun 1984 yang diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN). Fakta bahwa film ini diproduksi oleh BUMN perfilman dengan dukungan penuh negara menunjukkan statusnya sebagai proyek propaganda resmi pemerintah. Unsur hegemoni yang kuat dapat terlihat pada fakta bahwa film ini pada masa Orde Baru, tidak hanya dijadikan sebagai tontonan biasa layaknya film-film pada umumnya, tetapi film ini dijadikan sebagai tontonan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan ditayangkannya film tersebut di seluruh stasiun televisi setiap malam tanggal 30 September pukul 10:00 WIB. Sebuah survei pada 2002 menunjukkan bahwa sekitar 97 persen dari siswa yang disurvei telah menonton film ini, dan sekitar 87 persen dari mereka menontonnya lebih dari sekali.
Pada masanya, Film “Pengkhianatan G30S/PKI” dijadikan sebagai sumber sejarah satu-satunya yang dipergunakan. Masyarakat dilarang mendiskusikan isi film tersebut bahkan di ruang kelas sekalipun. Akibatnya, pengaruh dari strategi penayangan film ini sangat kuat, tertanam dalam benak masyarakat satu versi kebenaran yang tidak terbantahkan yakni PKI sebagai penjahat absolut dan pihak militer, khususnya Angkatan Darat pimpinan Soeharto adalah pahlawan penyelamat bangsa. Narasi film ini berhasil menciptakan trauma dan ketakutan mendalam terhadap segala hal yang berbau komunis. Bahkan, masyarakat masih mengkambing-hitamkan PKI sampai hari ini.
Seiring dengan akses informasi yang lebih terbuka dan perkembangan penelitian sejarah yang semakin mendalam, kritik terhadap film ini semakin masif. Namun, karena keterbatasan data dan dokumen-dokumen yang sulit diakses bahkan sengaja dihilangkan pada masa orde baru, penelitian sejarah yang objektif menjadi terhambat. Meskipun begitu, klaim film “Pengkhianatan G30S/PKI” sebagai representasi sejarah tetaplah diragukan karena banyak ditemukan kejanggalan dan dramatisasi yang tidak objektif.
Menguak Kontradiksi Film “Pengkhianatan G30S/PKI” dengan Realitas Sejarah
Kejanggalan yang ditemukan pada film “Pengkhianatan G30S/PKI” misalnya adegan penyiksaan terhadap perwira tinggi Angkatan Darat (AD) oleh para aktivis Gerwani. Digambarkan bahwa para jenderal diiris silet, dicungkil matanya serta alat kelamin mereka dipotong. Namun, laporan visum et repertum yang terdapat dalam buku sejarawan Ben Anderson menunjukkan fakta sebaliknya, yakni tidak ditemukannya bekas luka penyiksaan seperti penyiletan atau pencungkilan mata, melainkan jenazahnya dipenuhi luka tembak saja.
Adapun kejanggalan lainnya muncul pada penggambaran tokoh yang tak sesuai fakta, misalnya ketika ditampilkannya sosok Soekarno yang sedang sakit keras. Namun, kenyataannya dia berada dalam kondisi yang sehat. Hal ini terbukti dari kehadirannya pada acara seremonial pembukaan musyawarah nasional teknik di Istora Senayan pada 30 September 1965. Soekarno baru benar-benar sakit ketika sudah ditahan di Wisma Yaso, Jakarta. Selain pada tokoh Soekarno, ketidaksesuaian penggambaran tokoh pun dialami oleh DN Aidit sebagai pemimpin PKI yang dicitrakan sebagai sosok perokok. Hal ini banyak ditunjukkan ketika adegan-adegan ia sedang memimpin rapat dan memberikan instruksi kepada bawahannya. Padahal menurut sumber-sumber sejarah, Aidit sebenarnya bukanlah seorang perokok.
Terdapat peta Indonesia dalam salah satu adegan yang menampilkan ruang Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Hal yang menimbulkan pertanyaan adalah tampilan pada peta tersebut yang menunjukkan bahwa Timor Timur termasuk pada bagian dari wilayah Indonesia. Namun kenyataannya, pada saat G30S terjadi, Timor Timur masih berada di bawah kekuasaan penjajahan Portugis dan baru bergabung dengan Indonesia pada tahun 1975.
Baca Juga: Enam Tahun #ReformasjDikorupsi: Amanah 1998 dan Bayang–Bayang Orde Baru yang Kian Nyata
Dampak Hegemoni Rezim Orde Baru terhadap Peristiwa G30S
Dalam waktu beberapa bulan, setelah Soeharto berhasil menciptakan sebuah narasi yang menuduh PKI sebagai dalang utama di balik peristiwa keji G30S, terjadi pembersihan anti-komunis berupa pembantaian massal/genosida terhadap anggota PKI beserta orang-orang yang dituduh memiliki kaitan dengan komunis. Sebanyak 500.000 hingga 1 juta orang tewas akibat dari peristiwa ini. Menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu pelanggaran HAM yang sangat berat.
Upaya pembersihan yang dilakukan pada praktiknya tidak hanya ditujukan pada mereka yang berideologi komunis. Ini adalah strategi politik untuk melenyapkan semua pihak oposisi, terutama dari kalangan nasionalis kiri dan para simpatisan Soekarno. Akibatnya, sebagian besar dari korban adalah masyarakat sipil yakni petani, pendidik, buruh, dan seniman yang ditahan, disiksa, dan dibunuh tanpa proses pengadilan yang resmi. Tragedi ini diperburuk oleh ketiadaan proses hukum yang jelas dan adil bagi para korban dan keluarganya.
Hal paling tragis sebagai dampak dari peristiwa G30S adalah trauma mendalam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga saat ini, stigma terhadap komunis tidak pernah benar-benar lenyap. PKI tetap menjadi topik sensitif di Indonesia, serta segala hal tentang komunisme masih dianggap tabu. Hal ini menunjukkan bukti keberhasilan hegemoni Orde Baru dalam mengendalikan narasi sejarah sebuah bangsa.
Baca Juga: Mengingat Kembali: 21 Tahun Kematian Munir di Balik September Hitam
Penulis: Helma Mardiana
Editor: Ghaliah Syahiratunnisa