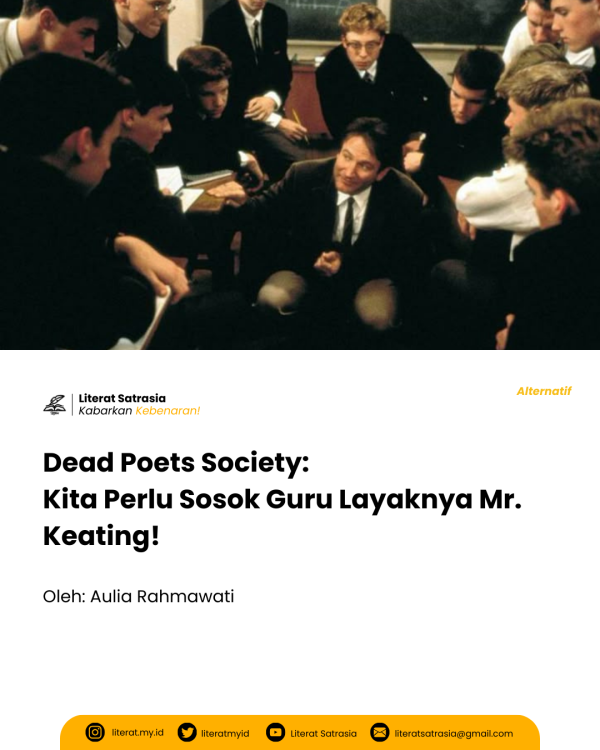La Haine (1995), masih menyisakan gaung yang kuat meskipun hampir tiga dekade berlalu sejak perilisannya. Disutradarai oleh Mathieu Kassovitz, film ini menyuguhkan gambaran tajam tentang kemarahan, ketidakadilan, dan ketegangan sosial di tengah realitas perkotaan yang penuh gejolak. Cerita yang disajikan berpusat pada kehidupan sehari-hari tiga pemuda di pinggiran Paris yang seakan-akan menjadi cerminan dari isu-isu sosial yang terus berulang: rasisme, diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan sistem yang menghantam komunitas-komunitas termarjinalkan. Selain itu, di masa sekarang ketika ketidaksetaraan ekonomi dan kebrutalan polisi masih menjadi perbincangan khalayak, La Haine tak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga teguran keras yang tetap bergema bagi hari-hari ini.
Cerita Tentang Sebuah Amarah
Film ini mengikuti satu hari dalam kehidupan Vinz (Vincent Cassel), Said (Saïd Taghmaoui), dan Hubert (Hubert Koundé). Tiga pemuda tersebut berasal dari latar belakang etnis dan agama yang beragam dan tinggal di lingkungan kumuh (banlieue) di pinggiran Paris.
Mereka hidup di tengah lingkungan yang penuh dengan frustrasi, di mana kekerasan, pengangguran, dan rasisme struktural adalah bagian dari keseharian. Narasi film dimulai setelah kerusuhan yang terjadi akibat kekerasan polisi yang meninggalkan seorang teman mereka, Abdel, dalam kondisi koma.
Dalam situasi yang membara ini, Vinz—karakter yang penuh dengan amarah dan kebencian terhadap polisi—bertekad untuk melakukan balas dendam jika Abdel meninggal. Sementara Said, yang lebih santai dan sering menghidupkan suasana dengan humor, berusaha menyeimbangkan ketegangan di antara mereka. Di sisi lain, Hubert, seorang petinju yang matang dan bijaksana, ingin meninggalkan lingkaran kekerasan ini dan mencari masa depan yang lebih baik. Namun, di tengah kebrutalan dan diskriminasi yang mengelilingi mereka, jalan keluar tampak semakin jauh.
Baca Juga: Lima Rekomendasi Puisi-Puisi Fenomenal W.S. Rendra yang Patut Dibaca
Ketiganya menavigasi kehidupan mereka dengan kebingungan dan kemarahan, seperti halnya masyarakat termarjinalkan di banyak kota besar di manapun. Saat kita melihat mereka berkeliaran di jalanan Paris yang seakan tak memberi ruang bagi mereka, selain ruang bagi kemarahan, tersirat bahwa mereka berada di jantung ibu kota Prancis, meskipun begitu mereka tetap merasa terasing dan terpinggirkan.
Hitam-Putih
Salah satu aspek paling mencolok dari La Haine adalah penggunaan sinematografi hitam-putih, yang memberikan suasana suram dan terkesan dokumenter. Dengan demikian pilihan ini menekankan nuansa kontras, antara mereka yang memegang kekuasaan dan mereka yang tidak punya pilihan selain berjuang di bawah struktur sosial yang menindas.
Dalam dunia hitam-putih ini, batas antara “benar” dan “salah” menjadi kabur. Kamera yang sering mengikuti karakter dari jarak dekat menciptakan rasa sempit dan menyesakkan sehingga memperkuat suasana mencekam film tersebut.
Visual yang monokrom ini juga menciptakan citra Paris yang tidak biasa: kota yang sering diasosiasikan dengan romantisme dan keindahan, di sini digambarkan dingin, keras, dan penuh permusuhan. Kassovitz seakan ingin menegaskan bahwa di balik gemerlap menara Eiffel dengan segala romantisasinya, ada sisi gelap yang jarang diperlihatkan. Ini adalah Paris yang berbeda, kota yang dipenuhi oleh kebencian dan frustrasi dari mereka yang tersingkirkan.
Tiga Karakter, Tiga Respons terhadap Ketidakadilan
Karakter utama dalam La Haine—Vinz, Said, dan Hubert—adalah representasi dari berbagai cara generasi muda menghadapi ketidakadilan sosial yang terus mendera. Vinz, dengan kemarahan yang meledak-ledak, mencerminkan jiwa muda yang merasa terpojok dan kehilangan harapan. Ketika kekerasan menjadi satu-satunya bahasa yang mereka pahami, Vinz mengira bahwa hanya dengan melawan balik, ia bisa memulihkan martabatnya. Namun, di balik amarahnya, Vinz sebenarnya terperangkap dalam ketidakberdayaan. Keinginannya untuk membalas dendam lebih merupakan ekspresi dari frustrasi yang sudah memuncak daripada rencana tindakan yang terencana.
Said, yang lebih ceria dan kerap membuat lelucon, seolah-olah menjadi penyeimbang diantara keduanya. Namun, meskipun Said tampak lebih santai, ia juga tak lepas dari tekanan kehidupan yang keras di pinggiran kota. Humor yang ia tampilkan adalah mekanisme bertahan hidup di tengah kerasnya realitas. Said adalah potret dari mereka yang memilih untuk bertahan dengan cara apa pun, bahkan jika itu berarti menertawakan ketidakadilan.
Sementara itu, Hubert adalah karakter yang paling rasional. Ia mewakili sisi kemanusiaan yang mencoba untuk tetap bertahan di tengah-tengah kehancuran. Selain itu, sebagai seorang atlet yang ingin keluar dari lingkaran kekerasan, Hubert adalah cerminan dari mereka yang berusaha mencari jalan keluar dari sistem yang rusak. Namun, seperti banyak karakter dalam film ini, ia pun akhirnya tak mampu menghindar dari realitas yang menjerat. Oleh karena itu, di akhir film, ketika segala usaha untuk menghindari kekerasan berakhir sia-sia, kita menyadari bahwa tak ada jalan keluar yang benar-benar terbuka bagi mereka.
Relevansi dengan Hari Ini
La Haine tidak hanya mengisahkan kemarahan di Prancis pada 1990-an, tetapi juga menggema di berbagai belahan dunia hari ini. Saat ini, kita masih menyaksikan protes-protes besar di kota-kota besar, seperti gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat yang menentang kebrutalan polisi dan rasisme, hingga demonstrasi-demonstrasi anti-kemiskinan diberbagai negara.
Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, serta antara yang berkuasa dan yang tertindas semakin melebar. Sehingga film La Haine tetap relevan di masa sekarang dan bahkan lebih fokus menyoroti isu sosial yang terjadi pada saat ini.
Situasi di Indonesia ini juga mencerminkan ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok-kelompok marginal di perkotaan. Ketika kita melihat ketimpangan sosial yang terus meningkat, peminggiran masyarakat urban, serta konflik yang kerap terjadi antara aparat keamanan dan warga di wilayah kumuh, narasi yang ditawarkan La Haine terasa sangat akrab. Oleh karena itu, film ini bukan hanya sekadar dokumentasi tentang sebuah masa, tetapi juga cermin dari kondisi masyarakat yang terus bergulat dengan masalah yang sama.
Di ujung film, Kassovitz meninggalkan kita dengan kalimat yang menghantui:
“Ini adalah kisah seorang pria yang jatuh dari gedung bertingkat lima puluh. Sambil jatuh, dia terus berkata, ‘Sejauh ini baik-baik saja’.”
Kalimat ini menjadi metafora bagi masyarakat kita hari ini—yang terus mengabaikan masalah yang semakin besar, hingga akhirnya kita bertabrakan dengan kenyataan yang keras.
Penulis: Reihan Adilfhi Tafta Aunillah
Editor: Diana
Baca Juga: Seni Reak di Terminal Ledeng, Wujud Rasa Syukur pada Alam Semesta