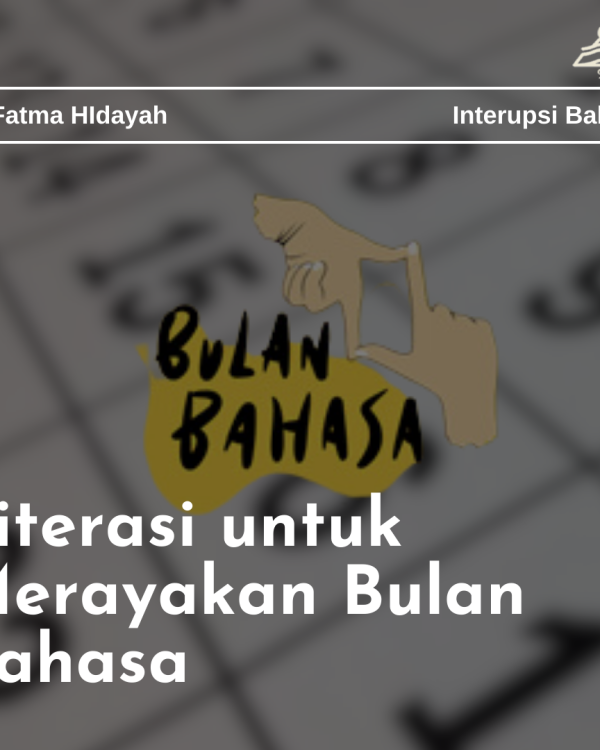Beberapa waktu lalu, gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak Agustus hingga September 2025 dari berbagai kota besar di Indonesia telah meninggalkan catatan buruk. Selain bentrokan antara aparat dan massa, hal tersebut juga dikarenakan penyitaan buku yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sejumlah massa ditangkap di tengah demonstrasi, sementara di sisi lain aparat sudah membawa sejumlah buku dari posko demonstran tanpa izin dari para pemiliknya.
Buku-buku yang dibawa oleh aparat kepolisian memiliki dalih bahwa bacaan tersebut terdapat hubungan ideologis dengan gerakan massa yang memicu kerusuhan. Terlebih dalam situasi politik yang bermasalah. Buku-buku itu dianggap dapat menjadi bukti keterkaitan antara gerakan intelektual dan tindakan anarki yang terjadi selama demonstrasi. Satu sisi lain, banyak akademisi dan masyarakat menilai penyitaan ini sebagai bentuk kriminalisasi gagasan. Mereka menegaskan bahwa buku bukanlah senjata, melainkan wahana berpikir yang seharusnya dilanggengkan oleh negara.
Kronologi dan Alasan Penyitaan
Penyitaan pertama kali dilaporkan terjadi di Jawa Barat pada pertengahan Agustus 2025 di mana polisi mengamankan beberapa buku dari lokasi demonstrasi mahasiswa di kawasan Dago, Bandung. Tak lama setelahnya, tindakan serupa muncul di Kediri dan Surabaya. Polisi menyebut buku-buku tersebut dijadikan dasar ideologi tersangka yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan.
Buku yang disita di antaranya:
- Menganggur dan Melawan Negara karya Bob Black,
- Anarkisme: Apa yang Sesungguhnya Diperjuangkan oleh Emma Goldman,
- Apa itu Anarkisme Komunis? karya Alexander Berkman,
- Kisah Para Diktator karya Jules Archer,
- Pemikiran Karl Marx yang diterjemahkan Franz Magnis-Suseno,
- Strategi Perang Gerilya karya Che Guevara,
- Jiwa Manusia di Bawah Sosialisme karya Oscar Wilde,
- Anak Semua Bangsa karya Pramoedya Ananta Toer,
- dan sejumlah buku bertema anarkisme seperti Menuju Estetika Anarkis, Why I Am Anarchist, serta Sastra dan Anarkisme.
Selain buku, beberapa pamflet dan poster juga disita, termasuk poster bergambar babi berjas bertuliskan “oligarki”. Menurut kepolisian, semua benda yang ditemukan di lokasi kerusuhan berpotensi menjadi barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP. “Apapun yang ada di tempat kejadian perkara dapat kami amankan untuk kepentingan penyidikan,” ujar Kapolri Listyo Sigit pada pertemuan diskusi dalam acara ROSI di Kompas TV (25/9/25).
Sejalan dengan ini, Polda Jawa Timur menyebutkan bahwa buku-buku tersebut dikategorikan sebagai barang bukti penyidikan untuk menelusuri apakah isi bacaan berpengaruh terhadap motivasi tindakan pembacanya. Polres Kediri juga menyatakan penyitaan dilakukan semata untuk kepentingan pendalaman kasus, sementara Polda Jawa Barat menilai beberapa buku yang dibaca para pelaku mengandung narasi yang dapat mendorong aksi kekerasan.
Namun, penjelasan itu tidak disetujui oleh publik. Banyak pihak menilai dalih hukum yang digunakan terlalu ambigu. Pasal 39 KUHP memang memungkinkan penyitaan terhadap barang yang berhubungan dengan tindak pidana, tetapi tidak ada ketentuan khusus yang menjelaskan bahwa buku bisa dijadikan bukti pidana kecuali barang tersebut secara langsung digunakan untuk merencanakan atau memerintahkan kejahatan.
Respons dari Kacamata Publik
Menanggapi hal ini, datang beberapa kritik dari akademisi, aktivis, hingga masyarakat sipil. Herlambang P. Wiratraman, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menilai tindakan penyitaan tersebut absurd dan ilegal. Menurutnya, aparat telah memperluas makna barang bukti secara berlebihan. “Buku adalah ide. Menyita ide sama artinya dengan menyita kebebasan berpikir,” ujarnya.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan KontraS juga menilai tindakan itu sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang mengancam hak asasi manusia. Mereka menegaskan bahwa penyidikan seharusnya berfokus pada tindakan nyata, bukan pada gagasan yang diinterpretasikan secara subjektif. LBH Jakarta bahkan menyebut pola penyitaan buku ini mengingatkan pada praktik lama ketika negara mengontrol bacaan publik melalui stigmatisasi ideologi tertentu.
Sementara itu, Brian Yuliarto selaku Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menyatakan dalam liputan Tempo (25/09/25) bahwa buku tentu harus sesuai dengan ketentuan bangsa dan ia berharap tidak ada buku yang melenceng dari ketentuan bangsa. Pernyataan ini memicu perdebatan baru bagi publik, banyak yang menilai negara tidak seharusnya menjadi penentu batas pikiran warganya.
Sejumlah pakar juga menyoroti beberapa posisi lemah perihal tindakan penyitaan ini. Pasal 1 nomor 16 KUHAP menjelaskan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda yang diduga secara langsung digunakan dalam tindak pidana atau diperoleh dari hasil tindak pidana. Buku, sebagai objek intelektual, berada di wilayah yang abstrak. Ia tidak memiliki hubungan langsung dengan tindakan fisik, kecuali jika terbukti digunakan untuk merencanakan atau mengarahkan kepada tindak kekerasan.
Ahli hukum tata negara dari Universitas Airlangga menegaskan bahwa penyitaan buku tanpa bukti keterkaitan langsung merupakan pelanggaran terhadap asas proporsionalitas dan presumption of innocence. Dalam negara hukum, pembatasan hak warga hanya sah jika dilakukan berdasarkan hukum yang pasti, bukan tafsir politis atau subjektif terhadap isi sebuah gagasan.
Baca juga: Makan Bergizi Gratis: Katanya Bergizi, Faktanya Kok Beracun?
Dampak Penyitaan
Jika dilihat melalui sudut pandang Pierre Bourdieu di dalam jurnal “Pierre Bourdieu dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik“, peristiwa pengambilan buku ini dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan simbolik, yaitu kekuasaan yang beroperasi secara perlahan melalui legitimasi pengetahuan serta materi bacaan. Negara, melalui aparatnya, memanfaatkan modal simbolik dalam bentuk kekuasaan hukum untuk menentukan bacaan mana yang dianggap sah atau berisiko.
Tindakan ini tidak hanya sebagai usaha pencegahan, tetapi juga sebagai cara mengendalikan masyarakat dalam melihat realitasnya. Melalui pengaturan bahan bacaan, negara dapat diindikasikan menjaga kekuasaannya dalam bidang pengetahuan. Di samping itu, langkah tersebut juga menciptakan habitus yang baru.
Masyarakat mulai berhati-hati saat membaca atau berdiskusi, bukan karena adanya larangan eksplisit, melainkan karena timbulnya rasa takut yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Habitus ini membuat cara berpikir menjadi terbatas, karena individu belajar beradaptasi dengan tekanan simbolik yang tidak kentara. Dalam situasi seperti itu, kebebasan berpikir secara bertahap memudar dan digantikan oleh budaya kepatuhan yang muncul dari perasaan takut.
Melalui teori field of cultural production dari “The Field of Cultural Production” karya Pierre Bourdieu, tindakan penyitaan buku juga memperlihatkan cara negara menjaga kekuasaannya dalam ranah budaya sastra yang mana penulis, penerbit, dan pembaca berada dalam posisi yang lemah dan tertekan struktur kekuasaan. Saat pengendalian atas pengetahuan dilakukan secara teratur, dinamika intelektual kehilangan kebebasannya. Narasi kritis yang seharusnya berkembang dari masyarakat akhirnya terbatasi oleh tekanan yang secara tidak langsung diciptakan oleh kekuasaan.
Akhirnya, dampak paling nyata terlihat pada budaya literasi. Di mana saat membaca dianggap berbahaya, minat baca dan kemampuan kritis masyarakat akan berkurang.
Menurut Bourdieu, modal kultural adalah faktor penting dalam terciptanya kesetaraan sosial. Maka, penyitaan buku juga berakibat pada terbatasnya akses terhadap modal kultural tersebut. Dalam jangka yang panjang, tindakan ini tidak hanya menghalangi perkembangan intelektual, tetapi juga memperlebar kesenjangan pengetahuan.
Trauma yang Belum Usai
Peristiwa penyitaan buku pada Agustus hingga September 2025 menunjukkan bahwa di tengah tuntutan reformasi, negara masih memandang ide sebagai sesuatu yang mengancam. Buku-buku yang seharusnya menjadi ruang introspeksi justru dijadikan barang sitaan, menandakan bahwa ketakutan terhadap suatu pikiran belum benar-benar hilang. Dalih hukum yang digunakan aparat memperlihatkan bahwa demokrasi kita masih rentan ketika kebebasan berpikir dibatasi oleh penafsiran yang subjektif.
Setiap tindakan penyitaan terhadap hal abstrak bukan hanya menghapus akses terhadap pengetahuan, tetapi juga menanamkan rasa takut di ruang-ruang belajar yang semestinya bebas dari pengawasan. Sejarah seharusnya menjadi pengingat agar kesalahan serupa tidak kembali terulang.
Dua dekade setelah reformasi, penyitaan buku dengan alasan ideologis memperlihatkan bahwa trauma lama belum sepenuhnya usai. Apa yang terjadi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan arah negara dalam menghargai perbedaan cara berpikir. Maka dari itu, buku bukanlah ancaman, tetapi yang berbahaya adalah saat kekuasaan merasa berhak mengatur isi kepala rakyatnya.
Penulis: Nabilah Novel Thalib
Editor: Aliyah Iffa Azahra