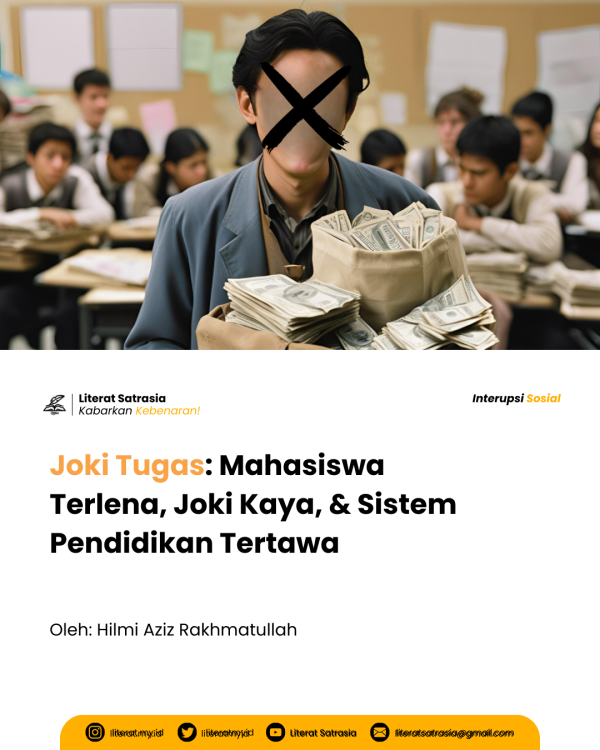Pada sebuah warung makan di daerah Ledeng, Bandung, Nurul Mimin Fadilah (19) sesekali menyeka keringat di dahinya. Di tengah deru bising wajan penggorengan dan panggilan pesanan yang tiada henti, ia harus berkali-kali meninggalkan obrolan kami, melayani pembeli yang datang silih berganti. Situasi yang hectic itu adalah rutinitasnya, sebuah ritme kehidupan yang jauh dari kemewahan masa muda.
Di sela waktu kosong menjelang Asar yang tenang sesaat, saya bertanya kepadanya.
“Adakah keinginan kuliah?”
Gadis lulusan SMK itu tersenyum tipis, matanya memancarkan kejujuran dan rasa rindu yang terpendam.
“Iya, ingin sekali. Jurusan seni, jadi guru vokal atau penyanyi,” harapnya.
Namun, keinginan dan mimpi Mimin terpaksa dikubur hidup-hidup karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu mengimbangi biaya pendidikan yang terlampau mahal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023/2024, rata-rata total biaya yang dikeluarkan peserta pendidikan tinggi di Indonesia mencapai Rp19,01 juta per tahun. Sementara itu, penghasilan keluarga Mimin bahkan tidak menyentuh UMR terkecil Provinsi Jawa Barat.
Pendidikan itu Kemewahan
Mimin adalah anak muda berpotensi dengan bakat suara yang bagus, terbukti dari ambisi yang ia simpan. Namun, ambisi itu tertutup rapat di dalam kulkas warung yang dingin. Saat teman-teman sebayanya sibuk memilih kampus, atau bebas bermain, ia sibuk memilah uang upah Rp1,5 juta per bulan untuk dikirim ke kampung halaman.
Kisah Mimin bukan cerita tunggal yang disebabkan oleh faktor keluarga semata. Ia adalah bagian dari data statistik yang mencoreng wajah pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2023/2024, tercatat lebih dari 1,2 juta anak lulusan sekolah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan lebih dari 1,1 juta anak lainnya terpaksa drop out di tengah jalan.
Seharusnya jutaan anak muda ini menikmati haknya yang dijamin melalui amanat konstitusi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Namun yang didapatkan ternyata nihil, mereka terpaksa menanggalkan mimpi. Menurut Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, mayoritas atau 76% keluarga mengakui alasan utama anak mereka putus sekolah adalah kendala ekonomi. Mereka tidak mampu membayar biaya sekolah, atau bahkan—seperti Mimin—harus mencari nafkah.
Inilah titik temu yang krusial: Kegagalan sistem dalam menjamin pendidikan yang layak bagi semua golongan. Mimin, dengan potensi dan bakatnya, dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Bukan hanya karena nasib keluarga, tetapi karena tembok struktural yang gagal menjamin akses pendidikan yang murah dan lapangan kerja yang adil.
Baca juga: Bocoran Anggaran Kemenkeu 2026: Pendidikan dan Kesehatan Bukan Lagi Prioritas Pemerintah, Warganet Protes
Berhenti dan Mati sebelum Memulai
Mimin bukanlah remaja yang malas. Ia adalah lulusan SMK jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) yang berprestasi di sekolah. Logikanya, ia memiliki potensi dan skill yang layak dipertimbangkan di pasar kerja yang lebih baik, atau setidaknya memiliki modal kuat untuk melanjutkan pendidikan tinggi di bidang seni yang ia idamkan.
Namun, potensi itu berhenti di garis start. Keadaan ekonomi keluarga menjadi tembok tebal yang tak terlintasi. Mimin pernah mencoba berdialog dengan nenek dan kakeknya—dua orang yang kini menjadi jangkar hidupnya—perihal kuliah. Jawaban yang ia dapatkan bukan penolakan, melainkan kalimat yang mematikan semangat.
“Nanti saja kalau sudah menikah, sekarang uang dari mana,” kata sang nenek.
Hal ini akhirnya menguatkan tekadnya untuk memilih mengorbankan impian, pergi merantau, dan bekerja keras.
Sejak lulus SMK, ia telah bekerja ke sana kemari, mulai dari sales di Pangandaran, Banyumas, hingga menjadi pelayan di Tasikmalaya, dan kini di Bandung. Semua demi menafkahi keluarganya.
Baca juga: Jika Semua Sekolah Sama, Mengapa Kesempatan Kita Berbeda?
Terdewasakan oleh Ketidakadilan
Keputusan Mimin untuk merantau dan bekerja adalah sebuah cerminan dari tragedi berlapis yang ia alami sejak usia belia.
Lahir dari keluarga sederhana yang tinggal di daerah Puspahiang, Tasikmalaya. Orang tua Mimin bercerai sebab si ayah berselingkuh. Sang ibu kandung memilih pergi ke kota besar, meninggalkan Mimin yang kala itu masih belum lancar berbicara. Kemudian, ayah Mimin menikah lagi. Di bawah bayangan ibu tiri, Mimin merasakan ketidakadilan dan kurangnya perhatian.
Titik terberat Mimin terjadi pada akhir masa SMP. Ayahnya, yang selama ini memperhatikan dan bahkan memondokkan dirinya, meninggal dunia. Setelah itu, ibu tirinya pun pergi begitu saja. Mimin pada akhirnya tinggal bersama nenek dan kakeknya yang sudah tua.
Di tengah situasi ini, Mimin mulai sering mendengar keluhan ekonomi dari bibi dan pamannya (adik-adik ayahnya). Hal-hal itu secara perlahan menanamkan pemikiran pada dirinya bahwa ia memikul tanggung jawab atas perekonomian keluarga.
Mimin menegaskan, keputusannya bekerja bukan karena dorongan dari keluarga, melainkan sepenuhnya karena perasaan sadar akan keadaan. Ia merasa bertanggung jawab membiayai kakek dan neneknya. Meskipun bibi dan pamannya kerap meminta bantuan finansial, Mimin mengaku ikhlas. Ia berpikir, dulu semasa sekolah mereka juga membantu sedikit-sedikit biaya pendidikannya.
Bagi Mimin, pengorbanan ini diwarnai motif spiritual yang mendalam. Ia berharap, kerja kerasnya membantu keluarga menjadi amal ibadah pengganti dosa-dosanya karena merasa akhir-akhir ini sering bolong-bolong shalat. Sebuah pengakuan yang menunjukkan beban ganda berupa ekonomi dan spiritual.
Namun, di tengah keikhlasan itu, ada satu hal yang kerap menyisakan luka. Ibu tirinya, yang pergi begitu saja pun terkadang meminta uang padanya. Padahal, selama ini ia tidak pernah memperhatikan Mimin dengan baik.
Baca juga: Potret Kesejahteraan Guru Honorer Saat Ini
Kegagalan Sistem yang Merampas Hak Usia
Kisah Mimin bukan sekadar tragedi personal. Ia adalah cerminan yang kasat mata dari kegagalan sistem keadilan sosial di Indonesia.
Bagaimana mungkin, seorang lulusan SMK dengan potensi dan skill TKJ yang seharusnya menjanjikan terpaksa menerima upah Rp1,5 juta per bulan? Sungguh jauh dari layak. Inikah akibat lowongan pekerjaan sulit dan sistem rekrutmen yang masih menjunjung nepotisme ‘orang dalam’? Lagi dan lagi, kegagalan struktural.
Sistem struktural di Indonesia memang sudah gagal menjamin hak dasar anak muda, yakni hak untuk berkembang dan berpendidikan. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi tangga mobilitas, namun tingginya biaya menjadikannya pagar pembatas bagi kalangan minoritas ekonomi. Seharusnya, orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan setinggi-tingginya kepada anak. Namun, realitasnya banyak anak muda di Indonesia—terutama dari keluarga broken home atau miskin—dipaksa menjadi ‘investasi’ yang harus segera menghasilkan.
Seandainya pemerintah mampu menjamin biaya pendidikan yang terjangkau bagi semua kalangan, lapisan kerja yang berlimpah dan transparan dan gaji yang layak sesuai kapasitas dan sektornya. Maka, ribuan ‘Mimin’ lainnya tidak perlu mengorbankan masa emas mereka di usia 19 tahun di balik meja warung. Padahal, potensi mereka adalah mengisi kursi kuliah atau bekerja di sektor yang layak.
Baca juga: Paradigma Transformasional Pendidikan Tinggi: Mengupas Arah Kebijakan Mendikti Saintek 2025
Memutus Rantai Kaum Sandwich
Di tengah getirnya realitas, Mimin menyimpan satu harapan besar yang menjadi motor penggerak perjuangannya.
“Saya ingin bekerja keras dan mengumpulkan uang sebanyaknya, agar suatu hari nanti jika saya punya anak, saya akan memberikan pendidikan dan kebebasan bermain kepadanya. Saya ingin anak saya merasakan euforia anak muda seusianya sesuai zamannya, agar tidak seperti diri saya.”
Mimin bertekad memutus rantai penderitaan dan beban ekonomi keluarga—rantai yang kerap mengikat kaum sandwich generation. Ia berjuang hari ini, agar generasi setelahnya mendapatkan kembali hak masa muda mereka yang telah dirampas darinya.
Di tengah aroma masakan yang mengepul, cita-cita seorang vokalis terpaksa sunyi dan gugur. Kisah Mimin adalah pengingat bahwa hak atas masa muda dan mimpi bukan hanya tanggung jawab individu sendirian. Bisa mewujudkan mimpinya juga merupakan tanggung jawab negara.
Penulis: Sabila Nurul Fadlillah
Editor: Muhammad Hilmy Harizaputra