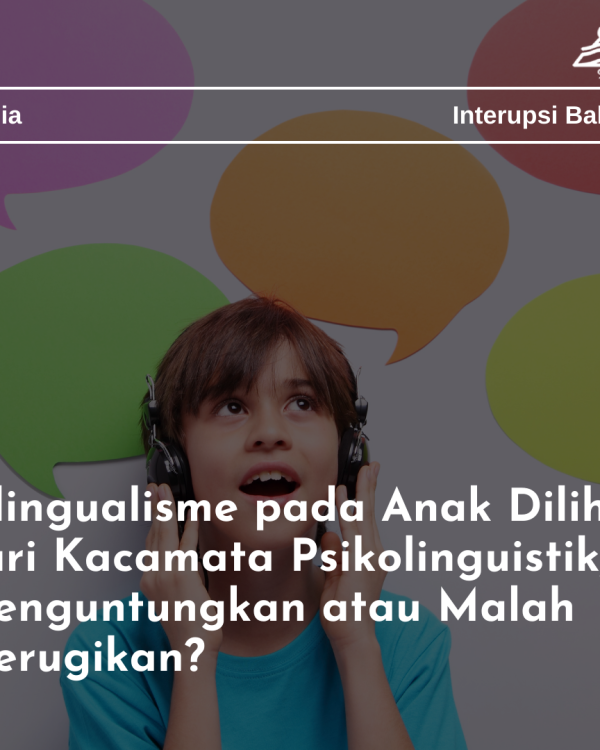Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh warga negara, termasuk anak-anak yang berada dalam situasi tidak menguntungkan, tetapi memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Namun, apakah ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut benar-benar sesuai dengan realitas saat ini? Atau justru ketimpangan pendidikan di Indonesia semakin nyata?
Masalah Berulang yang Tak Kunjung Usai
Permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia sepertinya selalu berkutat pada berbagai isu yang terus berulang. Mulai dari akses pendidikan yang terbatas, infrastruktur yang tidak memadai, ketidakmampuan secara ekonomi, kurangnya tenaga pendidik, upah tenaga pendidik yang tidak sesuai, hingga anggaran pendidikan yang terkadang tidak sesuai. Semua hal tersebut ibarat efek domino yang saling memengaruhi satu sama lain. Akses pendidikan yang sulit membuat pembangunan infrastruktur terhambat, sementara infrastruktur yang terhambat membuat tenaga pendidik tidak dapat bekerja secara maksimal.
Bahkan, sangat mudah untuk melihat betapa tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Mulai dari kisah siswa di pedalaman Kalimantan Selatan yang baru pertama kali menggunakan sepatu, sekolah tanpa tenaga pendidik di Nias, siswa tanpa seragam di Papua, pembelajaran yang hanya beratapkan terpal, hingga tenaga pendidik yang hanya bisa datang dua kali dalam seminggu. Fakta-fakta tersebut membuktikan betapa masih adanya ketimpangan yang sangat besar dalam sistem pendidikan di Indonesia.
Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya perhatian terhadap kualitas pendidikan di daerah terpencil. Banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas dasar seperti buku, meja, kursi, bahkan listrik. Kondisi ini tentu saja menghambat proses belajar mengajar dan membuat siswa sulit untuk bersaing dengan siswa dari daerah lain yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Tidak hanya itu, kurikulum yang sering berubah-ubah juga menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik dan siswa. Perubahan kurikulum yang tidak disertai dengan pelatihan yang memadai bagi tenaga pendidik, sering kali membuat proses pembelajaran menjadi tidak efektif.
Mempertanyakan Kesejahteraan Tenaga Pendidik
Masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik. Terlebih upah yang sering kali tidak sesuai dengan porsi kerja bisa jadi alasan mengapa minat menjadi tenaga pendidik terus menurun. Banyak tenaga pendidik, terutama yang mengajar di daerah terpencil, masih menerima gaji di bawah standar. Hal ini tentu saja memengaruhi motivasi dan kinerja mereka dalam mengajar. Belum lagi, beban administratif yang sering kali terlalu berat membuat tenaga pendidik tidak bisa fokus pada tugas utama mereka, yaitu mengajar. Kondisi ini diperparah dengan minimnya pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik. Padahal hal ini seharusnya menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Di sisi lain, anggaran pendidikan yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam memperbaiki sistem pendidikan sering kali tidak digunakan secara optimal. Di beberapa wilayah, penghasilan guru honorer masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR), berkisar antara Rp300.000 hingga Rp1.000.000 per bulan. Selain itu, ada kalanya dana pendidikan dialokasikan untuk hal-hal yang tidak relevan atau bahkan disalahgunakan oleh oknum tertentu. Hal ini tentu saja sangat merugikan karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, justru tidak sampai ke pihak yang membutuhkan. Artinya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
Baca Juga: Kondisi Pendidikan Indonesia Sekarang Beneran Seperti di Film?
Kesenjangan Kota dan Desa adalah Realitas
Tidak hanya itu, kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga semakin terlihat jelas. Sekolah di kota besar biasanya memiliki fasilitas yang lengkap dan tenaga pendidik yang berkualitas. Sementara sekolah di daerah pedesaan atau terpencil sering kali kekurangan fasilitas dan tenaga pendidik. Kondisi ini membuat siswa di daerah sulit untuk bersaing dengan siswa di kota besar, baik dalam hal akademik maupun non-akademik.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, sebanyak 5,11% penduduk desa tidak atau belum pernah sekolah, sementara di kota, angka ini jauh lebih rendah, yaitu hanya 1,93%. Hal ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan dasar di daerah pedesaan masih sangat terbatas dibandingkan dengan perkotaan.
Tidak hanya itu, ketimpangan juga terlihat pada tingkat kelulusan sekolah dasar. 12,39% penduduk desa tidak menamatkan pendidikan SD, sedangkan di kota, persentasenya hanya 6,62%. Angka ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi anak-anak di pedesaan untuk menyelesaikan pendidikan dasar, entah itu karena faktor ekonomi, infrastruktur, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.
Ketika melihat jenjang pendidikan menengah, kesenjangan semakin terlihat jelas. Hanya 27,98% penduduk desa yang berhasil menamatkan pendidikan SMA atau sederajat, sementara di kota, angka ini mencapai 49,16%. Artinya, hampir setengah penduduk kota memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengenyam pendidikan menengah, sementara di desa, mayoritas penduduk hanya mampu mencapai pendidikan dasar atau bahkan tidak bersekolah sama sekali.
Data-data ini menggambarkan betapa besar jurang ketimpangan pendidikan antara desa dan kota di Indonesia. Jika tidak segera diatasi, ketimpangan ini akan terus memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menghambat upaya pembangunan sumber daya manusia yang merata dan berkualitas.
Lalu, Apa yang Harus Dilakukan?
Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, maka perlu melakukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan semua pihak terkait. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien. Sayangnya, pemerintah justru memangkas anggaran pendidikan pada tahun 2025. Kedua, perlu ada program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama yang mengajar di daerah terpencil. Ketiga, pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan memastikan semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai. Keempat, perlu ada pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik agar mereka dapat mengikuti perkembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang terbaru. Meski tidak ada jaminan berhasil, setidaknya keempat langkah tersebut bisa diupayakan guna mengatasi masalah ketimpangan pendidikan di Indonesia.
Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam memperbaiki sistem pendidikan. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara memberikan dukungan moral dan material kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dapat berperan aktif membantu pemerintah mengatasi berbagai masalah pendidikan.
Dengan demikian, meskipun Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, realitas justru menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Hanya dengan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, sistem pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia dapat terwujud.
Penulis: Hilmi Aziz Rakhmatullah
Editor: Auliya Nur Affifah