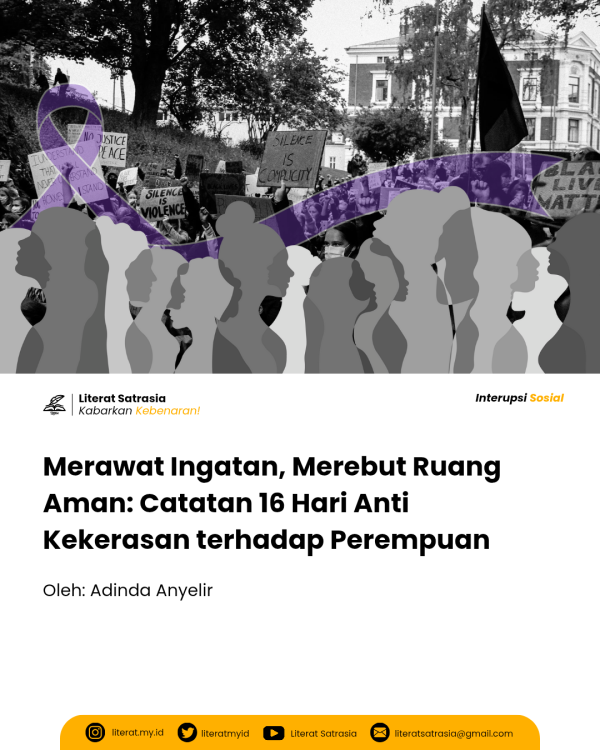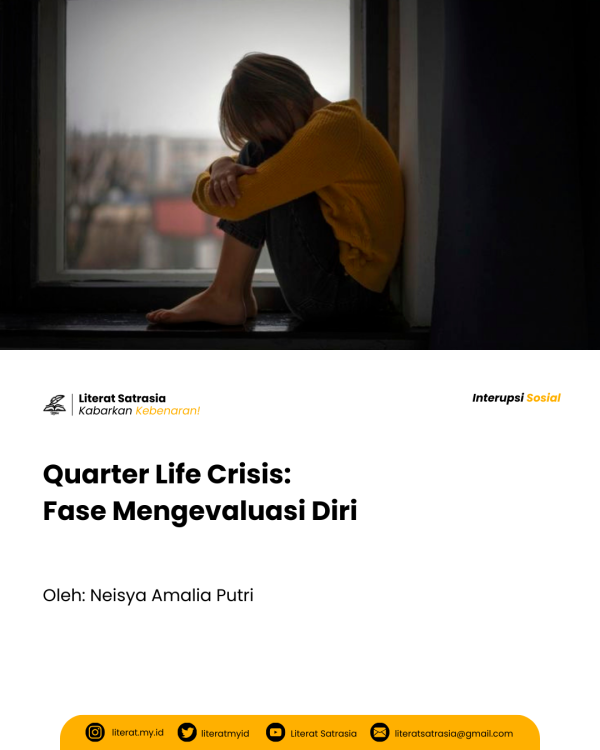Pangalengan, 19 September 2025 Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting Universitas Pendidikan Indonesia bersama FMN Cabang Bandung Raya, Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) UPI & BEM KEMA UNPAD menggelar kegiatan “Tiga Sama” pada 19–21 September 2025 di kawasan pertanian Pangalengan, Kabupaten Bandung. Program ini mengusung tiga prinsip utama: Sama Makan, Sama Tinggal, dan Sama Kerja sebagai bentuk nyata solidaritas mahasiswa terhadap perjuangan kaum tani.
Kegiatan ini melibatkan puluhan mahasiswa dari berbagai kampus seperti Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Politeknik Manufaktur Bandung yang secara langsung tinggal, makan, dan bekerja bersama petani setempat di Pangalengan. Mereka turun ke ladang, mengikuti alur kerja harian petani, sekaligus berdialog mengenai permasalahan agraria yang dihadapi masyarakat desa Margamekar.
“Lewat program Tiga Sama ini, kami ingin menghapus jarak antara mahasiswa dengan rakyat sektor petani. Mahasiswa tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari kenyataan hidup yang dihadapi petani sehari-hari”. Ucap Ketua Ranting FMN UPI, Miftahul Zamri saat berkebun di lokasi kegiatan. Sabtu (20/9/2025).
Program ini menjadi ruang belajar dan dialektis massa mahasiswa kepada kaum tani mengenai reforma agraria sejati, yang selama ini diperjuangkan oleh petani namun masih jauh dari harapan. Para peserta Tiga Sama mendapatkan pemahaman langsung mengenai ketimpangan kepemilikan lahan, konflik agraria,, ekonomi, dan tantangan dalam mempertahankan hak atas tanah. Selama tiga hari, para peserta tidak hanya bekerja di ladang, tapi tinggal di rumah warga khususnya di rumah Pimpinan Anak Cabang AGRA Pangalengan yaitu Bung Tarman dan Bung Rahma.
“Para mahasiswa ini sudah biasa main ke rumah saya khususnya anak UKSK UPI dan FMN untuk membawa semangat Hari Tani Nasional dan memperjuangkan Reforma Agraria Sejati”. Ujar Pimpinan Anak Cabang AGRA Pangalengan, Bung Tarman, saat makan bersama dengan mahasiswa.
Program Tiga Sama sendiri merupakan tradisi gerakan mahasiswa yang sudah lama dikenal sebagai metode pendekatan ekonomi-politik bagi mahasiswa ke akar rumput. Dengan menghidupkan semangat ini, mahasiswa diharapkan selalu menjadi garda terdepan dan menyokong semangat terciptanya Reforma Agraria Sejati.


| Kediaman Bung Tarman (Mr. Tarman’s residence) Margamekar Sabtu (20/9/25). (Foto: FMN) | Ladang Wortel (Carrot Fields) Margamekar Sabtu (20/9/25). (Foto: FMN) |
Baca juga: Ibu, Ojol, Penulis: Tiga Peran, Satu Nama
Ketimpangan Harga Jual dengan Pupuk Tani di Pangalengan
Bagi seluruh petani di Pangalengan, pupuk adalah kebutuhan paling pokok untuk menyuburkan tanah yang kemudian meningkatkan keberhasilan panen komoditas yang diperlukan pasar. Tanpa pupuk, hasil panen tidak akan maksimal; kualitas menurun, kuantitas merosot. Namun, seribu sayang harga pupuk terus melonjak justru tidak diimbangi dengan harga jual hasil panen yang stabil apalagi menguntungkan bagi petani.
“Si petaninya banyak hutang, harga jual murah. Jadi tidak seimbang antara pengeluaran dan produksinya jadi memang harus menanggung beban juga sebetulnya. Contoh harga tomat sekarang Rp1.500 an sampe Rp3.000 an sedangkan pupuk dan obat harganya lebih dari 100ribu-an per kilo jadi jauh bedanya.” lanjut Bung Tarman, petani sekaligus aktivis tani yang telah lama bersuara soal ketimpangan di sektor agraria. Pernyataannya muncul dalam diskusi hangat bersama kawan-kawan dari UKSK UPI dan BEM UNPAD yang tengah beristirahat di rumah Bung Tarman, Sabtu (20/9/2025).
Harga jual hasil pertanian yang rendah, sementara harga pupuk dan kebutuhan produksi lainnya terus melonjak, menjadi beban berat bagi petani di Pangalengan. Kondisi ini mendorong mereka masuk dalam lingkaran ketergantungan yang menyulitkan. Kenaikan biaya produksi terutama untuk pupuk dan pestisida membuat banyak petani terpaksa mengandalkan utang dari koperasi maupun tengkulak demi bisa tetap bertanam. Namun ironisnya, saat masa panen tiba, harga hasil pertanian justru sering jatuh, akibat spekulasi pasar, kebijakan impor yang tidak berpihak pada petani lokal, serta terbatasnya akses petani ke pasar tanpa perantara
Diskusi ini juga menyoroti bagaimana bantuan pupuk susbsidi yang dijanjikan negara belum menjawab persoalan akar, karena distribusinya yang tidak merata ke seluruh petani, tidak tepat sasaran, dan rawan dimonopoli pihak-pihak tertentu. Padahal, basis pertanian di Pangalengan termasuk basis pertanian skala regional dan nasional yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah.
Bung Tarman menegaskan bahwa hanya reforma agraria sejati yang mampu menyelamatkan pondasi pertanahan dan masa depan pertanian di Indonesia. Menurutnya, inti dari reforma agraria sejati adalah merebut kembali tanah-tanah dalam penguasaan besar baik oleh korporasi, tuan tanah, maupun negara untuk kemudian didistribusikan kepada kaum tani yang secara langsung menggantungkan hidupnya pada tanah. Dengan demikian, akses dan kontrol atas tanah benar-benar berada di tangan mereka yang menggarap, bukan di tangan pemodal atau elite kekuasaan (20/9/2025).
Taqi, perwakilan dari UKSK UPI, menambahkan bahwa perjuangan reforma agraria sejati tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan aktif mahasiswa. “Kami meyakini bahwa mahasiswa harus berpihak pada rakyat tertindas, dan dalam konteks hari ini, petani adalah yang paling ditindas oleh sistem agraria yang timpang dan penuh manipulasi. Perjuangan kaum tani adalah panggilan moral bagi kami, kaum terpelajar, untuk tidak diam,” ujarnya saat diskusi lapangan bersama petani Pangalengan Sabtu (20/9/2025).
Taqi juga menegaskan bahwa solidaritas mahasiswa dan rakyat harus dibangun dalam aksi nyata, bukan hanya dalam ruang akademik. “Reforma agraria sejati adalah fondasi kedaulatan nasional. Kalau mahasiswa benar-benar ingin perubahan, maka berpihak kepada perjuangan petani adalah keharusan, bukan pilihan,” tegasnya.

| Hasil panen kentang (Potato Harvest) Margamekar, Minggu (21/9/25). (Foto: Muhammad Suyadi Badar/Literat) |
Apa sih Reforma Agraria Sejati itu?
Perjuangan untuk menuntut Reforma Agraria Sejati mulai menguat pada awal era Reformasi, khususnya sejak tahun 1999. Salah satu tonggak penting dalam gerakan ini adalah berdirinya organisasi tani bernama Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), yang secara resmi dideklarasikan di Wonosobo, Jawa Tengah, pada tahun 2004. Pendirian AGRA lahir dari semangat Reformasi Mei 1998 dan menjadi wujud nyata dari konsolidasi gerakan tani nasional. Saat itu, sekitar 15.000 petani dari berbagai daerah di Indonesia turut serta dalam aksi deklarasi sebagai bentuk solidaritas dan perlawanan terhadap sistem feodalisme di pedesaan. Momen tersebut menjadi simbol penting akan perlunya gerakan massa yang berwatak anti-feodal dalam memperjuangkan hak-hak demokratis rakyat, khususnya hak atas tanah sebagai kebutuhan paling mendasar bagi kaum tani. Sejak 2004 hingga kini AGRA eksis memperjuangkan hak-haknya kaum tani dan gerakan penghormatan terhadap hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat kecil.
Reforma agraria sejati merupakan suatu gerakan yang secara langsung menentang praktik monopoli tanah oleh kelompok-kelompok berkuasa seperti tuan tanah besar, kapitalis birokrat, dan borjuasi besar komprador. Tujuan utama dari gerakan ini adalah mengambil alih penguasaan tanah yang sangat luas tersebut untuk kemudian diredistribusikan kepada kaum tani yang benar-benar membutuhkan akses dan kontrol atas tanah. Saat ini, praktik monopoli tanah telah mencapai skala ratusan juta hektar, yang tersebar dalam bentuk berbagai konsesi dan izin, seperti perkebunan besar, pertambangan, kawasan hutan, proyek-proyek infrastruktur, hingga skema lingkungan seperti restorasi ekosistem dan kawasan taman nasional.
Di samping perjuangan untuk reforma agraria sejati, kaum tani Indonesia juga perlu mengambil bagian aktif dalam mendorong industrialisasi nasional bersama gerakan buruh. Industrialisasi nasional adalah proses membangun industri yang berpihak pada kepentingan rakyat, terutama kaum tani dan buruh, bukan pada kepentingan asing atau elite ekonomi. Ini mencakup pengambilalihan kembali aset-aset kekayaan nasional yang selama ini dikuasai oleh korporasi asing, serta pengembalian dana hasil korupsi ke kas negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan karakter yang berpihak pada kedaulatan dan kepentingan mayoritas rakyat, industrialisasi nasional merupakan bagian dari gerakan anti-imperialis yang menolak dominasi asing atas sumber daya dan arah pembangunan Indonesia.
Dalam konteks saat ini, berbagai institusi pendukung kapitalisme monopoli, termasuk pemerintahan yang dinilai sebagai representasi kekuatan imperialisme seperti pemerintahan Prabowo-Gibran juga mengusung program reforma agraria. Namun, implementasinya kerap bersifat manipulatif dan jauh dari esensi reforma agraria sejati. Salah satu aktor utama kapitalisme global seperti World Bank yang mendorong konsep pasar tanah (land market) sebagai pengganti reformasi distribusi tanah (land reform) yang sejati. Konsep ini diwujudkan melalui berbagai program pinjaman dan bantuan teknis yang diberikan kepada negara-negara setengah jajahan dan setengah feodal seperti Indonesia, salah satunya melalui skema Proyek Administrasi Pertanahan (Land Administration Project). Program-program semacam ini justru memperkuat liberalisasi sektor pertanahan dan mengaburkan tujuan utama reforma agraria: menghapus ketimpangan dan memberikan tanah kepada mereka yang menggarapnya.
Baca juga: Analisis Wacana Kritis dari Pernyataan Prabowo terkait Demo di X
Agraria Palsu, Petani Tertipu
Sejalan dengan arah kebijakan Proyek Administrasi Pertanahan yang didorong oleh World Bank, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga menjalankan program reforma agraria. Namun, program tersebut lebih menitikberatkan pada sertifikasi tanah, yang kemudian diklaim sebagai bentuk redistribusi tanah. Padahal, pendekatan ini jauh dari semangat reforma agraria sejati. Bahkan, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pemerintah justru menetapkan bahwa tentara, polisi, pegawai negeri sipil, hingga badan usaha dapat menjadi subjek penerima reforma agraria. Perumusan subjek semacam ini tidak hanya menyimpang, tetapi juga memutarbalikkan makna utama reforma agraria, yang seharusnya ditujukan untuk kaum tani tak bertanah atau bertanah sempit.
Lebih jauh, program ini juga tidak menyentuh akar persoalan utama, yakni monopoli penguasaan tanah dalam skala besar oleh korporasi dan elit pemilik moda yang biasanya dikuatkan oleh lembaga terkait seperti, PT. Perkebunan Nusantara, Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Taman Nasional. Alih-alih menghapus ketimpangan, reforma agraria versi pemerintah justru berpotensi memperkuat struktur kepemilikan tanah yang timpang. Dengan melihat arah kebijakan dan implementasinya, program pasar tanah yang didorong oleh Bank Dunia (World Bank) maupun program reforma agraria di era pemerintahan Jokowi layak dikategorikan sebagai reforma agraria palsu. Keduanya tidak menyasar akar ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah, dan justru memperkuat mekanisme pasar dalam pengelolaan agraria. Hal serupa juga terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), di mana Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dijalankan dengan pendekatan serupa memanipulasi semangat reforma agraria sejati demi kepentingan birokrasi dan pasar, bukan untuk menjawab kebutuhan kaum tani tak bertanah.
Sejarah Reclaiming Tanah Sampalan
Di balik hamparan hijau ladang sayur di Pangalengan, Kabupaten Bandung, tersimpan sebuah kisah perlawanan yang menggugah. Bukan hanya soal bertani dan panen, tapi soal tanah, hak, dan perjuangan panjang kaum tani miskin untuk mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Pada awal tahun 2000-an, kehidupan petani kecil di Desa Margamekar, Pangalengan, tidak pernah mudah. Banyak dari mereka hanya menjadi buruh tani yang bekerja di lahan milik perusahaan daerah, pengusaha kaya, atau tuan tanah lokal. Mereka diupah murah, hidup tanpa kepastian, dan tidak memiliki tanah sendiri. Padahal, tanah yang mereka garap sebenarnya merupakan tanah negara, yang dikuasai melalui berbagai konsesi atau perjanjian tak adil sejak lama.
Pada tahun 2003, buruh tani di Pangalengan mendirikan Forum Tani Pangalengan (FTP) untuk membangun solidaritas di antara petani miskin. Dukungan datang dari tiga aktivis mahasiswa Front Indonesia Muda (FIM) Bandung yang tinggal bersama masyarakat setempat, yaitu Wowon, Jumarlis, dan Rahmad. Awalnya, FTP berencana mengembangkan pertanian organik sebagai solusi atas mahalnya harga pupuk dan obat. Namun, karena mayoritas anggota adalah buruh tani tanpa lahan, mereka beralih pada gagasan yang lebih besar: merebut tanah negara yang dikuasai perusahaan daerah dan petani kaya. Meski sempat diragukan oleh para aktivis mahasiswa, para petani tetap ngotot melakukan reclaiming, yakni mengambil alih tanah milik negara untuk dikelola bersama. Setelah melakukan investigasi status lahan, mereka mengajukan usulan resmi kepada kepala desa agar dibuat Peraturan Desa untuk reforma agraria, namun ditolak aparat desa. Penolakan ini mengingatkan pada sejarah aksi sepihak tahun 1960-an, ketika petani yang tergabung dalam Barisan Tani Indonesia (BTI) merebut tanah secara paksa. Meskipun demikian, semangat FTP untuk menuntut hak atas tanah tetap menyala, menjadi bagian penting dari perjuangan reforma agraria sejati di Pangalengan.
Dari situ, muncul kesadaran: “TANAH HAK UNTUK RAKYAT”. Maka, lahirlah Forum Tani Pangalengan (FTP), sebuah organisasi petani yang kemudian menjadi bagian dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) sebuah organisasi nasional yang lahir dari semangat Reformasi 1998. FTP menjadi kendaraan perjuangan petani Pangalengan untuk merebut kembali hak atas tanah. Namun perjuangan mereka tidak serta-merta dilakukan dengan konfrontasi langsung. FTP membangun kekuatan dari bawah. Mereka menyelenggarakan pendidikan hukum agraria, mengkaji status tanah, mengorganisir massa tani, dan melakukan konsolidasi dalam pertemuan rutin mingguan. Semua dilakukan agar langkah mereka sah secara hukum dan kuat secara politik.
Puncaknya terjadi pada 10 Juli 2004, ketika ratusan petani melakukan reclaiming atau pengambilalihan lahan di kawasan Sampalan. Sekitar 40 hektar lahan yang sebelumnya dikuasai oleh PDAP (Perusahaan Daerah Agribisnis dan Perkebunan) secara simbolik dan nyata mulai digarap oleh petani FTP. Mereka menanam jagung, pisang, dan singkongbukan hanya untuk kebutuhan makan, tapi sebagai simbol bahwa tanah ini kembali digarap untuk hidup, bukan untuk laba. Mereka juga memasang plang besar bertuliskan, “Tanah Hak untuk Rakyat.” Pesan ini jelas: petani bukan pencuri tanah, mereka sedang merebut haknya yang dirampas. Setelah aksi reclaiming, FTP menghadapi banyak tekanan. PDAP mencoba menggugat balik secara hukum. Aparat desa dan pihak keamanan melakukan intimidasi. Tapi para petani tetap bertahan, menjaga ladang secara kolektif, membagi hasil panen bersama, dan menolak sistem sewa-menyewa atau pembelian yang hanya menguntungkan elite. Hingga beberapa tahun kemudian, sebagian dari lahan tersebut tetap berhasil mereka kelola, meski belum ada legalitas yang kuat. Mereka tidak memiliki sertifikat, tidak punya status resmi, tapi mereka punya kontrol: tanah dikelola oleh mereka yang mengerjakannya. Perjuangan FTP menunjukkan bahwa reforma agraria sejati bukanlah soal sertifikat semata, melainkan bagaimana tanah bisa betul-betul dikuasai dan dimanfaatkan oleh kaum tani. Sebaliknya, reforma agraria versi negara yang hanya berwujud sertifikasi tanah tanpa menyentuh persoalan monopoli, hanyalah topeng dari sistem agraria yang tetap timpang.
Hari ini, saat harga pupuk melonjak dan harga jual hasil tani terus ditekan, kisah perjuangan petani Pangalengan kembali relevan. Mereka telah menunjukkan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan agraria bisa dilakukan dengan pengetahuan, organisasi, dan keberanian. Mereka tidak menunggu negara, mereka bergerak sendiri.
Baca juga: Puisi “Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia”
Refleksi Pentingnya Reforma Agraria Sejati bagi Keadilan Sosial dan Pembangunan Pertanian
Reforma agraria sejati bukan sekedar pembagian tanah, melainkan sebuah langkah fundamental mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan pertanian di Indonesia. Tanah yang selama ini dikuasai secara monopoli oleh borjuasi besar, elite politik, dan pengusaha kaya harus kembali ke tangan petani kecil yang menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut.
Keadilan sosial akan terwujud ketika petani memiliki akses dan kontrol penuh atas tanahnya, mampu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan mendapatkan hasil yang layak dari jerih payahnya. Selain itu, reforma agraria sejati membuka peluang bagi pembangunan pertanian yang mandiri dan berdaya saing, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Tanpa reforma agraria sejati, ketimpangan kepemilikan tanah akan terus memperlebar jurang sosial dan memperlemah sektor pertanian sebagai basis ekonomi rakyat. Oleh karena itu, perjuangan reforma agraria sejati adalah perjuangan untuk masa depan bangsa yang lebih adil, makmur, dan demokratis.
Ladang sayur itu bukan hanya ladang pangan. Ia adalah ladang perlawanan, ladang harapan, dan ladang masa depan.
Penulis: Muhammad Suyadi Badar