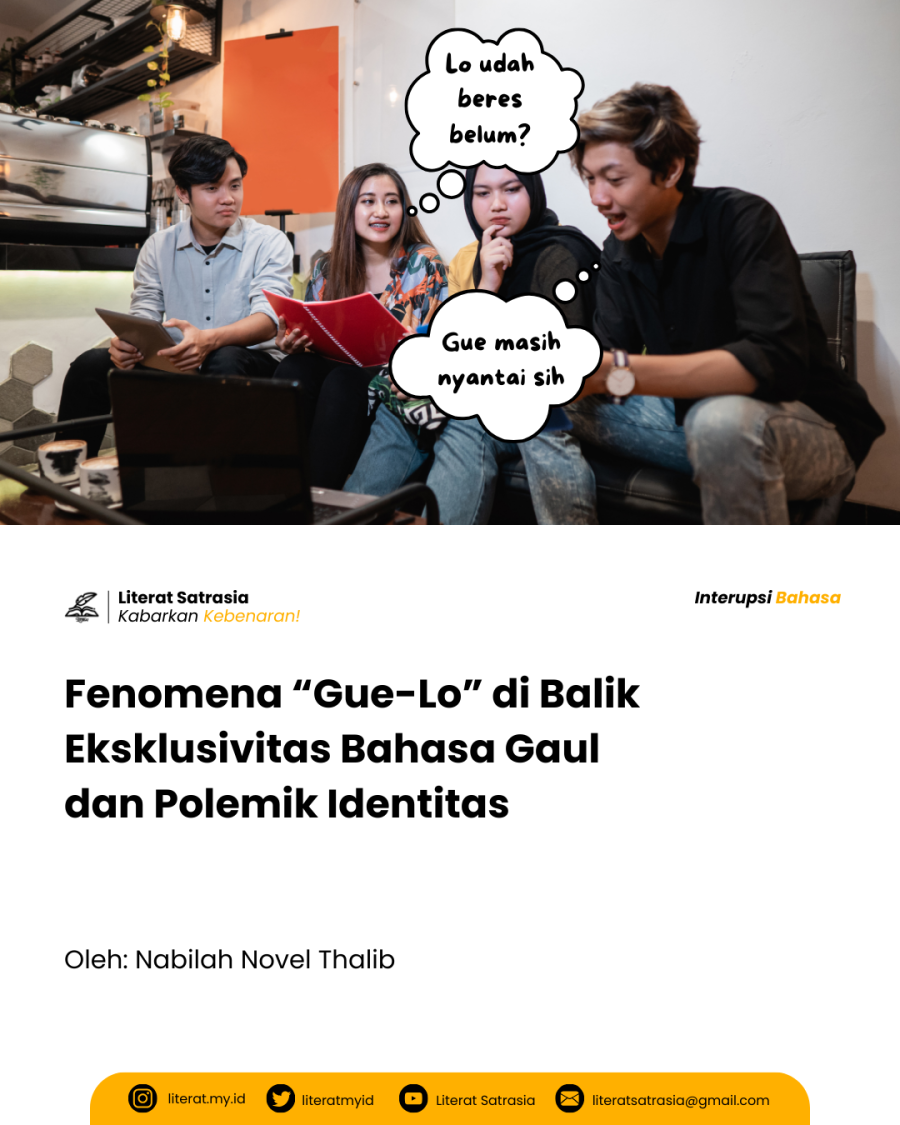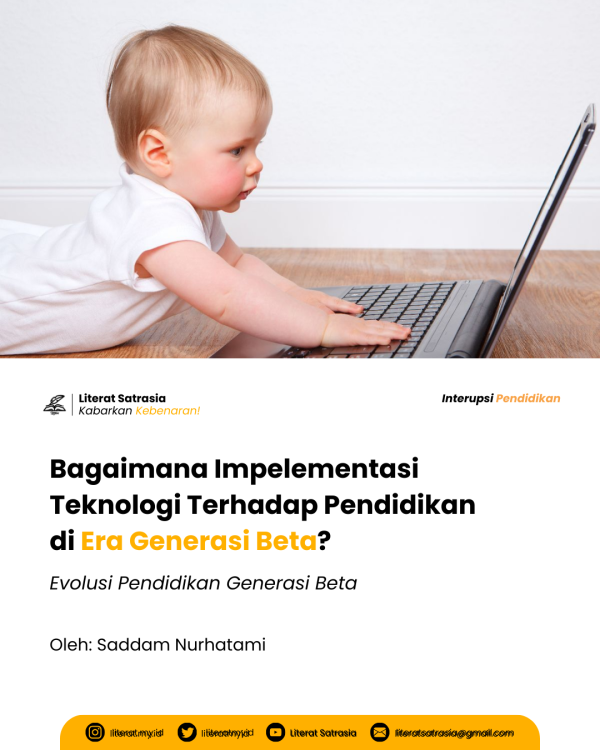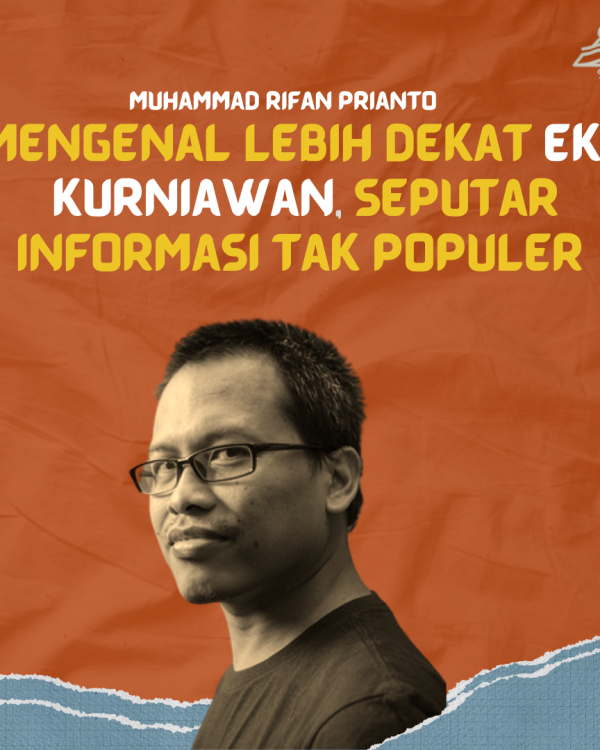Gemuruh kehidupan terus berjalan, mengharuskan setiap makhluk berkomunikasi sebagai penggerak laju roda peradaban. Dalam berkomunikasi, bahasa menjadi salah satu elemen terpenting. Bahasa tak sekadar menjadi sarana komunikasi, melainkan cerminan dari keberagaman budaya yang memperkaya identitas suatu bangsa.
Dilansir dari situs pusat penelitian bahasa Ethnologue, Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara dengan bahasa terbanyak di dunia per 29 Juli 2024, yakni mencapai 724 bahasa. Keberagaman bahasa ini menjadi aset yang tidak ternilai. Namun, keberagaman ini diindikasikan sebagai alasan utama atas munculnya fenomena suatu bahasa daerah diadopsi menjadi bahasa pergaulan lintas wilayah. Salah satu contohnya adalah penggunaan ungkapan “gue-lo”, sebuah ciri khas dari bahasa Betawi yang kini kian beken di berbagai kalangan luar Jakarta. Fenomena ini memicu beragam tanggapan mengenai eksklusivitas bahasa, mulai dari apresiasi hingga kontroversi.
Baca Juga: Melihat Bagaimana Dominasi dan Dampak Bahasa Nasional terhadap Bahasa Daerah – Literat
Polemik Bahasa dalam Studi Kasus @Convomf
Wadah digital X kerap kali menjadi ruang diskusi dunia maya yang menyoroti berbagai isu, salah satunya isu bahasa. Di akun menfess populer seperti @Convomf, banyak unggahan yang membahas keresahan terhadap orang non-Jakarta yang menggunakan ungkapan “gue-lo”. Hal ini dipantik oleh tweet berikut:
“Sender kira yg pakai ‘gua/gue-lu/lo’ di twitter itu orang asli Jabodetabek, ternyata pas ditanya domisili rata-rata orang Jowo, agak kaget.” (@Convomf, 2025).
Beberapa pengguna bernada mengamini, menyebut bahwa bahasa memiliki elemen eksklusivitas, sementara yang lain berpendapat sebaliknya. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, bahasa daerah seperti Betawi semakin banyak digunakan di luar daerah asalnya dan bisa diklasifikasikan sebagai bahasa gaul. Namun, apakah kehadiran bahasa lintas wilayah ini akan diterima oleh seluruh kalangan atau malah menimbulkan ketimpangan berbahasa?
Bagaimana Mahasiswa Memandang Eksklusivitas Bahasa?
Kedaton, mahasiswa asal Salatiga, berpendapat, “Jika seseorang lahir dan besar di tanah Betawi, dia pasti berbahasa dan berdialek Betawi asli seperti yang bisa kita lihat pada tokoh Mandra dalam film Si Doel Anak Sekolahan. Misalkan saya biasa menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu, tetapi dihadapkan dengan pengguna bahasa Sunda campur bahasa Betawi gaul. Banyak yang seperti itu, apalagi teman asal Jabodetabek. Rasanya agak tabrakan, tapi mereka juga engga mempermasalahkan, jadi kebawa lucu dan seru aja kalau dengar cara bicaranya.”
Sejalan dengan pendapat di atas yang mengamini penggunaan bahasa Betawi bukan merupakan eksklusivitas bahasa, di mana hanya bisa digunakan oleh orang-orang Jabodetabek, terkhusus Jakarta. Caca, mahasiswa asal Depok beranggapan, “It’s okay jika orang Betawi ataupun bukan menggunakan bahasa Betawi karena bahasa tersebut masih universal di Indonesia. Saya sendiri yang besar dalam lingkup Betawi tidak mempermasalahkan hal tersebut.”
Di sisi lain, ada perspektif berbeda, “Menurut aku keren aja sih, tapi ngga semua orang. Jujur kalau orang daerah yang pake kadang kurang cocok, apalagi orang yang udah kita kenal dan biasa pake bahasa daerah terus tiba-tiba ngomong gue-lo, kadang telinga ini butuh penyesuaian. Bisa jadi awkward kalo lawan bicara pake gue-lo, sedangkan aku pake aku-kamu,” jelas Alya, mahasiswa asal Sumedang.
Sementara itu, Nadia, mahasiswa asal Banten, mencoba menanggapi fenomena ini dengan netral, “Penggunaan kata gua lo ini aku rasa ga masalah dipakai semua orang karena udah ada hilirisasi dan gue lo ini masuknya udah bahasa gaul. Dilihat dari perspektif orang Jabodetabek itu sendiri, aku rasa ga ada judging dari mereka kalau kita pake gue lo, tapi ya emang balik lagi ke pribadi masing-masing.”
Baca Juga: Xenoglosofilia: Berkah atau Ancaman bagi Bahasa Indonesia? – Literat
Alat Pemersatu atau Ketimpangan Berbahasa?
Perdebatan tentang “gue-lo” mencerminkan dinamika unik dalam masyarakat Indonesia yang heterogen nan multikultural. Fenomena adopsi bahasa atau ungkapan dari budaya tertentu oleh masyarakat luas menandakan penerimaan budaya. Di sisi lain, penggunaan bahasa tanpa pemahaman yang berdasar dapat dianggap sebagai bentuk ‘apropriasi’ budaya, misalnya hanya untuk terlihat keren.
Bagi masyarakat Betawi, ungkapan “gue-lo” bukan hanya sekadar bahasa gaul, melainkan bagian dari sejarah dan tradisi yang sudah mengakar secara turun-temurun. Ketika ungkapan ini digunakan oleh orang dari luar budaya tersebut, ada kekhawatiran bahwa nilai-nilai budaya yang melekat di dalamnya akan terkikis karena penyelewengan fungsi oleh beberapa oknum tanpa pemahaman yang berdasar.
Menurut Koentjaraningrat (1992:15), bahasa adalah bagian dari kebudayaan. Dengan demikian, penggunaan bahasa seperti “gue-lo” tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai budaya yang melingkupinya. Penggunaan bahasa oleh orang tanpa pemahaman konteks yang tepat dapat dianggap sebagai minimnya penghormatan terhadap etik kebudayaan asal yang terus diregenerasi.
Mencari Titik Temu
Perdebatan seputar penggunaan ungkapan “gue-lo” seharusnya tidak hanya dipandang dari satu sisi saja. Kita harus menempatkan bahasa sebagai ruang dialog, bukan sebagai sumber perpecahan. Alih-alih memandang penggunaan bahasa lintas budaya sebagai bentuk penggerusan nilai budaya, hal ini justru dapat mempererat hubungan antarsuku yang memiliki bahasa serta dialek beragam. Dengan catatan, penggunaan bahasa harus tetap digunakan dengan rasa hormat terhadap asal-usul empunya.
Salah satu cara untuk mencapai titik temu adalah dengan meningkatkan literasi budaya dalam masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Literasi budaya tidak hanya mengajarkan asal-usul sebuah bahasa atau ungkapan, tetapi juga nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Dengan pemahaman yang lebih dalam, setiap individu dapat menggunakan bahasa lintas wilayah secara bijak tanpa mengurangi esensi budaya yang melingkupinya.
Bahasa Sebagai Cermin Peradaban
Bahasa adalah saksi bisu perjalanan sebuah peradaban. Setiap kata, ungkapan, atau dialek membawa nilai-nilai kehidupan dan cerita tentang masa lalu. Dalam konteks Indonesia, keragaman bahasa merupakan warisan yang tak ternilai, simbol dari harmoni dalam keberagaman. Ungkapan seperti “gue-lo” bukan hanya sekadar bagian dari bahasa gaul, tetapi juga wujud bagaimana budaya Betawi merespons modernisasi tanpa kehilangan identitas. Ketika ungkapan ini diadopsi oleh masyarakat dari luar wilayahnya, hal ini menjadi bukti pengaruh budaya yang dinamis.
Peristiwa bahasa seperti ini mengajarkan pentingnya menghormati keberagaman dan menjaga nilai-nilai luhur dalam setiap langkah peradaban. Penggunaan ungkapan “gue-lo” seharusnya menjadi dorongan kita untuk terus belajar, memahami, dan merayakan keberagaman budaya dalam bingkai persatuan. Namun, hal ini juga menjadi pengingat bahwa bahasa tidak berdiri sendiri; ia selalu terikat dengan nilai dan sejarah yang melahirkannya.
Baca Juga: Menjadi Bahasa Resmi ke-10 di UNESCO: Apa Konsekuensinya? – Literat
Penulis: Nabilah Novel Thalib
Editor: Mahmudah Salma Nur Iftikhar