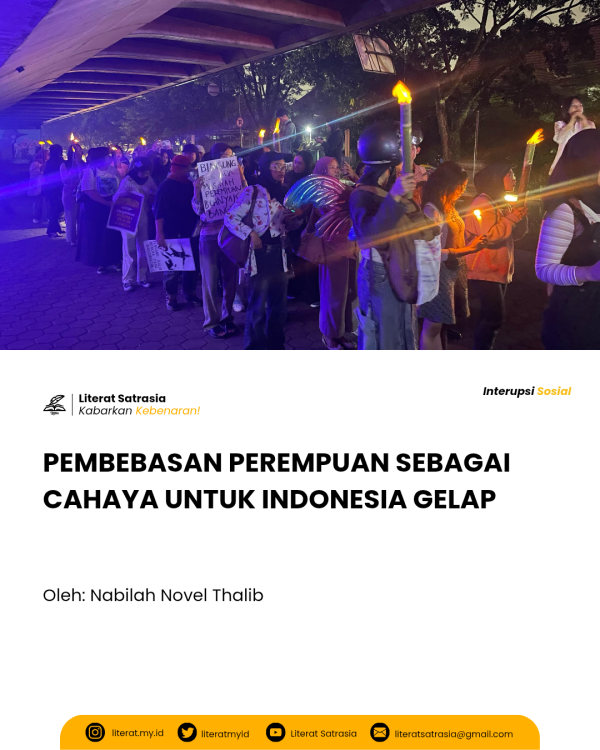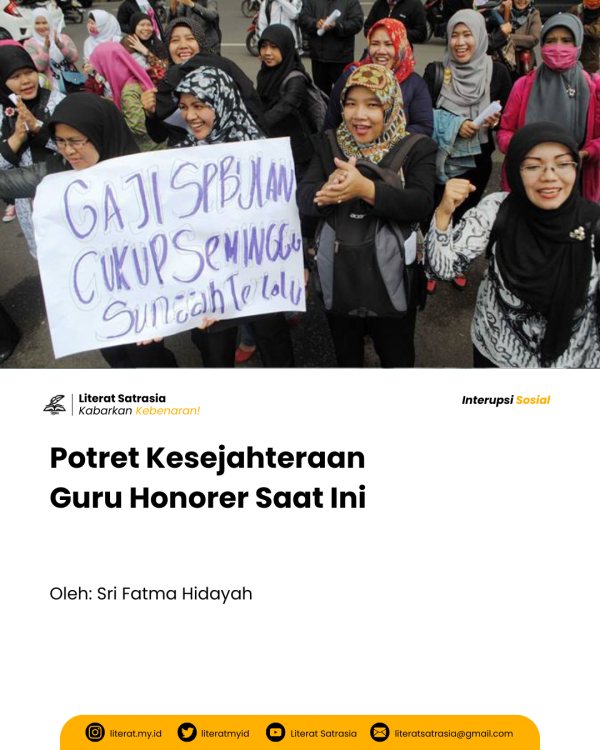Hari Buruh Internasional, May Day diperingati setiap 1 Mei. May Day bukan hanya sekadar seremoni aksi turun ke jalan. Ia adalah suara kolektif dari jutaan buruh yang selama ini hidup dalam ketimpangan. Tahun ini, di berbagai kota di Indonesia, termasuk Bandung, suara itu kembali bergema. Ribuan peserta aksi berkumpul di Taman Cikapayang Dago (1/5) menyuarakan aspirasi mereka. Ada yang tanpa membawa spanduk dan tanpa pengeras suara. Hanya dengan suara jujur dan mata yang tak lagi muda.
Banyak yang datang dari pekerjaan sebagai petugas kebersihan outsourcing di lingkungan instansi besar. Dengan upah minim, mereka bekerja tanpa adanya asuransi kesehatan, tanpa kontrak kerja, dan tanpa akses koperasi yang bisa jadi penyambung napas saat kebutuhan mendesak datang. Mereka, seperti banyak buruh lainnya, hanya bisa bertahan.
“Gaji kecil bukan cuma bikin hidup susah. Tapi juga bikin kita nggak punya pilihan”, sahut salah satu buruh aksi.
Pernyataan tersebut menjadi pintu masuk untuk memahami betapa besar dampak dari sistem ketenagakerjaan yang timpang ini. Dalam kasus tersebut, outsourcing bukan sekadar bentuk kontrak kerja. Ia adalah realitas hidup yang menciptakan keterbatasan demi keterbatasan.
Baca Juga: Debut single pertama “RE-PEACE” dengan judul “Tak Ada Yang Mengerti” – Literat
Outsourcing dan Ketimpangan Upah
Sistem outsourcing telah lama dipraktikkan di berbagai sektor industri dan layanan publik. Sederhananya, outsourcing memungkinkan perusahaan untuk menyerahkan pekerjaan tertentu kepada pihak ketiga guna menekan biaya produksi. Sayangnya, efisiensi ini sering dibayar mahal oleh para pekerjanya.
Pekerja outsourcing cenderung menerima upah lebih rendah dari pekerja tetap meski beban kerja yang ditanggung setara, bahkan kadang lebih berat. Mereka juga kerap tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti jaminan kesehatan, tunjangan hari raya, cuti tahunan, hingga perlindungan hukum yang kuat.
Lebih dari itu, hubungan kerja outsourcing memunculkan rasa keterasingan dan minoritas. Mereka bekerja dalam sebuah institusi, tetapi tidak benar-benar menjadi bagian dari institusi itu. Tidak heran jika mereka merasa seperti “numpang kerja”.
Dampak Upah Kecil terhadap Pendidikan
Dampak dari sistem kerja semacam ini tidak berhenti pada urusan dapur rumah tangga. Hal tersebut justru berpengaruh pada aspek yang lebih fundamental: pendidikan.
Pendidikan seharusnya menjadi jalur keluar dari kemiskinan. Namun, ketika upah tak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar, bagaimana bisa keluarga menyisihkan untuk biaya pendidikan? Banyak anak dari keluarga buruh terpaksa berhenti sekolah lebih awal. Beberapa bahkan tidak mampu membeli buku, mengikuti les, atau membayar iuran kegiatan sekolah yang semestinya jadi bagian dari proses pembelajaran.
Situasi ini mencerminkan secara langsung apa yang menjadi kekhawatiran global, sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-4: Quality Education. Tujuan ini menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dari keluarga miskin dan pekerja informal.
UNICEF menyebut pendidikan sebagai kunci untuk mobilitas sosial. Tanpa pendidikan, anak-anak tidak akan bisa keluar dari lingkaran kemiskinan yang diwariskan. Namun, dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, pendidikan justru semakin sulit dijangkau. Hal tersebut menciptakan siklus stagnasi sosial: orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, lalu anak-anak itu tumbuh dalam keterbatasan yang sama, dan seterusnya.
Upah Kecil dan Stagnasi Ekonomi
Selain pendidikan, upah kecil juga memengaruhi roda ekonomi secara luas. SDGs poin ke-8, yakni Decent Work and Economic Growth, menjadi konteks penting dalam hal ini. Tujuan ini menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan pekerjaan yang layak.
Ketika buruh hidup dengan upah pas-pasan, daya beli mereka melemah. Keluarga hanya fokus bertahan hidup, bukan berkembang. Tidak ada ruang untuk investasi kecil seperti usaha rumahan, simpanan darurat, atau pengembangan keterampilan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas bawah stagnan dan ketimpangan makin melebar.
Baca Juga: Calling for All Writers: Tips n Trick Naskahmu Di-publish Gramedia! – Literat
Lebih jauh, upah rendah juga berdampak pada industri. Buruh yang tidak sejahtera cenderung tidak loyal, sering berpindah kerja, atau mengalami penurunan produktivitas karena tekanan mental dan fisik. Semua ini sebenarnya menciptakan biaya tak kasat mata yang lebih besar bagi perusahaan dan industri secara keseluruhan. Menjadi narasi bahwa efisiensi biaya melalui outsourcing dapat mendukung pertumbuhan ekonomi perlu dikritisi.
Refleksi dan Ajakan Perubahan
May Day bukan sekadar momentum tahunan. Ia adalah ruang untuk refleksi sosial, sekaligus desakan perubahan. Kita harus melihat bahwa sistem kerja yang timpang dan upah yang minim tidak hanya menciptakan masalah sosial jangka pendek, tetapi juga mengancam masa depan bangsa.
Sudah waktunya negara hadir lebih kuat. Regulasi mengenai sistem kerja outsourcing harus ditinjau ulang. Perlu ada penetapan standar minimum hak-hak buruh outsourcing yang wajib dipenuhi oleh industri maupun penerima jasa. Selain itu, perlu adanya dorongan politik dan kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih aman dan adil.
Dunia pendidikan pun perlu menjangkau lebih dalam, terutama pada anak-anak dari keluarga buruh. Program beasiswa, subsidi sekolah, dan pendekatan sosial berbasis komunitas bisa menjadi jembatan bagi mereka yang selama ini mengalami kesulitan. Lembaga pendidikan tinggi, seperti universitas negeri, bisa mengambil peran lewat jalur afirmasi khusus untuk anak-anak dari keluarga rentan.
Masyarakat sekitar pun memiliki peran penting. Kita bisa mulai dengan membangun empati dan solidaritas. Menolak diskriminasi terhadap pekerja outsourcing, mendukung kampanye perlindungan buruh, hingga memberikan ruang untuk mereka bercerita, adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih manusiawi.
Mimpi Itu Belum Mati
Di antara riuhnya aksi May Day kemarin, suara para buruh mungkin tak sekeras orasi para aktivis. Tapi mereka tetap datang. Dengan langkah pelan, mereka membawa harapan dan tuntutan yang tak kalah penting untuk bisa hidup layak, menyekolahkan anak, dan tidak terus-menerus hidup dalam ketidakpastian.
Sistem yang adil bukan hanya soal upah layak, tetapi tentang keberpihakan pada manusia terutama para pekerja yang selama ini menjadi penopang keseharian kita. May Day adalah pengingat bahwa kesejahteraan bukan sekadar angka IPM di laporan ekonomi, tetapi tentang hidup yang lebih bermartabat bagi seluruh elemen masyarakat.
“Is Not an Act of Charity, It Is an Act of Justice”
– Nelson Mandela
Baca Juga: Alegori Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Novel “Animal Farm” Karya George Orwell – Literat
Penulis: Icha Nur Octavianissa
Editor: Rifa Nabila