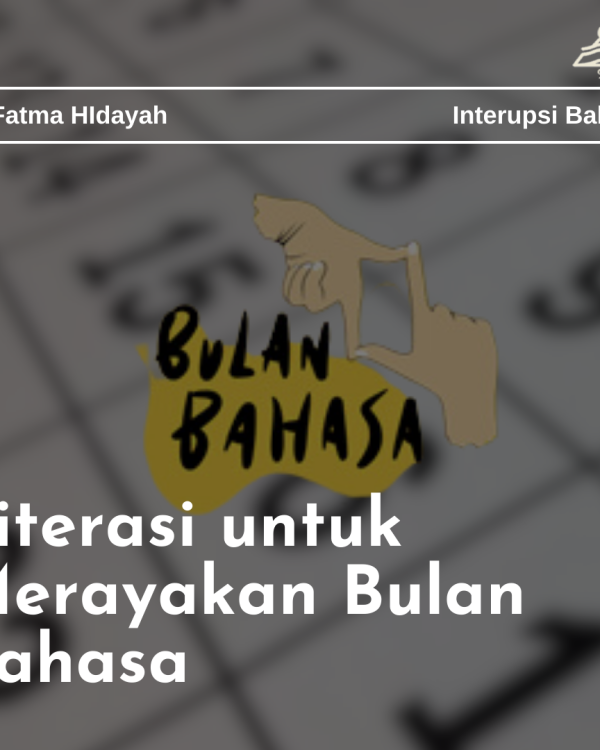Curhat di media sosial sudah menjadi bagian dari keseharian generasi muda masa kini. Unggahan status, caption foto, hingga cuitan di X sering kali berisi potongan emosi, keresahan, atau kisah harian yang ingin dibagikan kepada publik. Menariknya, baik saat curhat di media sosial maupun ketika berbagi cerita secara personal dengan teman dekat, banyak anak muda kerap menyisipkan bahkan sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris secara spontan.
Sejatinya, Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita. Namun, kenyataanya banyak anak muda lebih nyaman mengungkapkan isi hati dalam Bahasa Inggris, terutama untuk topik-topik yang sensitif. Mengapa bisa begitu? Apakah ini soal gaya, pengaruh budaya, atau ada faktor psikologis yang lebih dalam?
Yuk simak beberapa penjelasan yang bisa menyingkap fenomena ini!
Bahasa Inggris Sebagai Filter Emosi
Menggunakan Bahasa Inggris saat curhat dapat berfungsi sebagai emotional filter. Selain itu, bahasa non-ibu juga bisa membantu seseorang menjaga jarak emosional dari perasaan negatif dan lebih mudah mengendalikan perasaan. Sebuah studi yang dikutip dari Frontiers in Psychology menyebutkan bahwa individu bilingual cenderung mengalami penurunan intensitas emosional saat menggunakan bahasa kedua dalam situasi stres atau penuh tekanan (Caldwell-Harris, 2015).
Hal ini selaras dengan pendapat Rudy, seorang pengguna Quora. “It is the way my brain works. Saya lebih fasih berbahasa Inggris dalam hal tertentu dan fasih berbahasa Indonesia dalam hal lain.”
Dalam percakapan sehari-hari, pernyataan seperti, “I’m just emotionally drained” terasa lebih ringan diucapkan ketimbang, “Aku bener-bener lelah secara emosional”. Bukan karena artinya berbeda, tetapi karena nuansa emosinya lebih tersekat. Bahasa Inggris dalam hal ini menjadi “baju pelindung” agar curhatan tidak terasa terlalu “telanjang”.
Selaras dengan hal tersebut, Khoyyiroh Zatil Aqmar atau yang akrab dipanggil Zatil, Mahasiswa program studi Teknik Geologi Universitas Padjajaran, mengungkapkan, “Menurut saya pribadi, beberapa kata dalam Bahasa Indonesia rasanya agak berlebihan untuk mengekspresikan perasaan saya. Kesannya kadang terlalu puitis, dramatis, atau lebay. Contohnya, saat ingin mengungkapkan perasaan: ‘aku merasa sedih’, sedih kenapa? Seakan-akan perasaan saya seperti ingin menangis, padahal kenyataannya saya cuma merasa tidak enak. Jika di dalam Bahasa Inggris: ‘i feel bad’, lebih detail karna bukan sedih, tapi hanya sedang merasa sedikit tidak baik saja.”
Dalam sudut pandang Psikologi, konsep penyaringan perasaan ini juga dijelaskan, “Kecenderungan curhat dalam bahasa asing agar tidak terlalu gamblang punya pola yang mirip dengan disavowal, di mana individu secara tidak sadar meminggirkan sebagian emosi yang seharusnya dirasakan. Keadaan ini biasa terjadi sebagai bentuk respons terhadap kecemasan agar individu tidak merasa berlebihan atau lebay, juga agar luka batin tidak terasa begitu menyakitkan,” ungkap Najwa Azizah Nathania, mahasiswa program studi Psikologi, Universitas Pendidikan Indonesia.
Idiom dan Ekspresi yang Lebih Fleksibel
Bahasa Inggris memiliki banyak ungkapan idiomatik yang ekspresif dan efisien. Ungkapan seperti “it hits different”, “emotionally drained”, atau ungkapan sayang seperti “I love you” terasa lebih ringkas, tapi sarat makna. Sementara itu, dalam Bahasa Indonesia, kadang kita perlu lebih banyak kata atau penjelasan untuk menyampaikan hal serupa.
Fenomena ini juga erat kaitannya dengan budaya pop dari lagu, film, buku, hingga konten Tiktok dan Instagram yang kebanyakan diakses dalam Bahasa Inggris. Akibatnya, idiom dan gaya bahasa tersebut ikut membentuk cara kita berpikir dan merespons situasi emosional.
Zatil juga turut mengungkapkan pendapatnya tentang seberapa berpengaruh budaya pop tersebut, “Budaya pop sangat berpengaruh karena pengaruh budaya yang sering dikonsumsi dapat diserap oleh otak secara otomatis karena terbiasa berbahasa dengan bahasa asing,” ucap Zatil.
Dalam hal ini, Bahasa Inggris bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga gaya berekspresi yang dianggap lebih pas untuk situasi tertentu, khususnya di ruang digital yang serba cepat, singkat, dan padat makna.
Code-Switching dan Faktor Lingkungan
Banyak anak muda hidup di lingkungan bilingual, pergantian kode bahasa (code-switching) menjadi hal wajar. Ini bisa disebabkan oleh pendidikan, komunitas, atau kebiasaan sehari-hari. Ketika curhat, seseorang terkadang tanpa sadar menyisipkan Bahasa Inggris. Misalnya, “Ya, aku ngerti sih dia enggak salah, but still hurts, you know?”
“Saya merasa bahwa sekarang ini bukan hanya di tempat formal saja Bahasa Inggris digunakan, dalam kehidupan sehari-hari pun Bahasa Inggris sering digunakan. Salah satu contohnya ada di Jakarta Selatan, di mana saya sewaktu berkunjung ke sana sering mendengarkan banyak orang yang menggunakan Bahasa Inggris yang dicampur-campur dengan Bahasa Indonesia,” ungkap Gustav Alden yang memberikan pendapatnya dalam sebuah unggahan di Quora tentang “Mengapa Kebanyakan orang Indonesia Lebih Suka Menggunakan Bahasa Inggris daripada Bahasa Indonesia dalam Bersosial Media?”
Meskipun unggahan itu ditujukan untuk konteks media sosial, mekanismenya tetap relevan dalam percakapan personal sebagaimana tanggapan yang diberikan Gustav. Ketika lawan bicara juga terbiasa menggunakan Bahasa Inggris–tinggal di lingkungan bilingual–percakapan campuran justru terasa lebih lancar dan ekspresif. Generasi muda masa kini menggunakan code-switching sebagai strategi untuk menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan psikologis, termasuk saat berbagi emosi.
Bahasa Inggris Meningkatkan Rasa Percaya Diri
Menggunakan Bahasa Inggris juga sering kali dikaitkan dengan citra diri. Di kalangan anak muda urban, bahasa ini bukan hanya sarana komunikasi, tapi juga simbol modernitas, keterbukaan, dan kemampuan. Tanpa disadari, ini menumbuhkan motivasi untuk menggunakan dalam berbagai konteks, termasuk saat curhat. Hal ini menunjukkan kemampuan berbahasa dan rasa percaya diri.
Gustav juga menambahkan bahwa, “Saya rasa penggunaan Bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari sampai di dalam media akan memberikan kesan keren dan gaul banget.”
Namun, penting diketahui, penggunaan Bahasa Inggris dalam konteks ini tidak selalu berarti ingin pamer atau terlihat lebih unggul. Beberapa orang yang memang belajar atau bekerja dalam lingkungan bilingual membuat mereka terbiasa menggunakan Bahasa Inggris.
Apakah Bahasa Indonesia tetap Relevan dalam Mengekspresikan Diri?
Meskipun tren menggunakan Bahasa Inggris cukup marak, bukan berarti Bahasa Indonesia kehilangan tempatnya. Ada banyak situasi di mana curhat menggunakan bahasa ibu justru terasa lebih tulus, hangat, dan menyentuh. Misalnya, ketika berbagi cerita masa kecil, membicarakan keluarga, atau menyentuh pengalaman spiritual.
“Aku bener-bener merasa sendiri, tapi enggak tahu harus cerita ke siapa.”
Kalimat tersebut terasa sangat dekat secara emosional. Dalam konteks ini, Bahasa Indonesia memiliki daya ungkap yang kuat dan akrab. Bahkan dalam dunia psikologi, banyak konselor menyarankan klien untuk berbicara dalam bahasa ibu ketika ingin menggali emosi terdalam. Hal ini karena bahasa yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari cenderung lebih jujur menyampaikan perasaan.
“Berdasarkan beberapa temuan dalam literatur konseling dan psikologi, penggunaan bahasa ibu memang dianggap lebih jujur dalam menyampaikan perasaan, terutama perasaan spiritual. Hal ini disebabkan karena kedekatan bahasa ibu dengan identitas dan pengalaman individu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, penggunaan bahasa asing dalam sesi curhat atau konseling itu melahirkan jarak emosional yang menyebabkan adanya pengabaian atau penekanan terhadap emosi itu sendiri,” ungkap Najwa.
Pilihan Bahasa adalah Pilihan Rasa
Pilihan bahasa saat curhat, baik dalam percakapan langsung maupun melalui teks, bukan sekadar soal kemampuan atau gaya. Ini adalah refleksi dari perasaan yang ingin dilindungi, dijelaskan, atau dibagikan dengan cara yang paling aman.
Bahasa Inggris membantu menjaga jarak emosional, menyampaikan ekspresi dengan lebih fleksibel, dan tetap terlihat tenang. Sementara itu, Bahasa Indonesia tetap menjadi jembatan kuat untuk kedekatan batin, budaya, dan kehangatan personal. Dalam urusan rasa, bukan soal mana bahasa yang lebih baik, melainkan mana yang paling pas untuk membuat kita didengar dan dipahami.
Penulis: Azila Fitria Ramadhani
Editor: Nabilla Putri Nurafifah