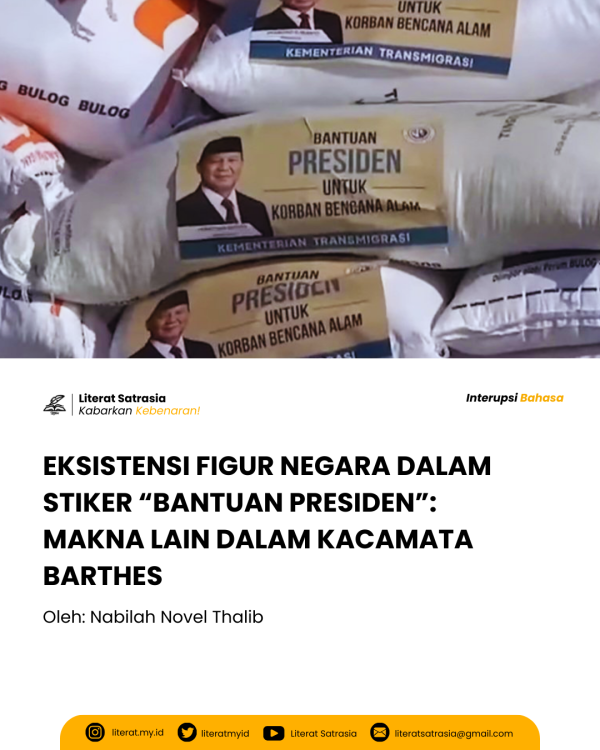“Orang bilang tanah kita tanah surga
tongkat kayu dan batu jadi tanaman.”
– Kolam Susu, Koes Plus
Prolog
Tanah menjadi sesuatu yang sangat penting. Sejarah mencatat, tanah menjadi sumber dari kebutuhan dasar manusia: sandang, pangan, dan papan. Begitu pula hari ini. Makannya, tanah menjadi sesuatu yang sangat mahal dan diperebutkan oleh banyak orang (dengan memiliki kepentingan apapun).
Mari kita sedikit flashback. Pada zaman sebelum adanya tulisan, orang-orang biasa memanfaatkan tanah sebagai proses kesehariannya. Seperti yang saya singgung di muka, tanah menjadi tempat di mana sandang, pangan, dan papan berasal. Sandang terbuat dari daun-daun dan akar-akar pohon, serta kulit hewan. Pangan berasal dari hewan dan tanaman-tanaman. Apalagi saat manusia sudah mulai bisa mandiri dalam hal pangan (food producing), tanah menjadi sesuatu yang vital. Papan, tempat di mana kita bermukim juga berdiri di atas tanah. Baik itu gua-gua, perkakas, perabot, dan tektek bengek lainnya.
Maju ke masa feodalisme atau kerajaan. Tanah yang berada di wilayah kerajaan, khususnya tanah pertanian, menggunakan sistem appanage. Sistem ini menjadikan tanah yang awalnya dimiliki oleh kerajaan, diberikan kepada pejabat atau orang-orang tajir kala itu. Timbal baliknya, pemilik tanah mesti membayar upeti kepada kerajaan dalam bentuk hasil bumi yang telah dikumpulkan oleh petani (di sini petaninya terdiri dari kaum papa).
Masuk ke masa kolonialisme atau penjajahan. Bangsa-bangsa luar mulai ngeh dengan magisnya tanah Indonesia. Inggris adalah negara beruntung pertama. Saat itu, Raffles menerapkan teori Domein. Apaan tuh? Teori domein ini tidak berbeda jauh dengan praktik pada tanah hari ini. Kalau kawan-kawan mesti membayar pajak untuk kepemilikan tanah, nah itu adalah teori domein. Jadi, domein adalah bayaran yang mesti disetorkan kepada pemerintah atas tanah dan hasil tanah.
Masa kolonialisme tidak berhenti di sana. Saat Belanda yang memimpin, Van den Bosch, menerapkan sistem culturstelsel atau tanam paksa. Saya yakin teman-teman sering mendengar istilah tersebut. Saat itu, tanah dapat ditransfer ke pihak lain dengan syarat mematuhi kebijakan dari ordonansi. Misalnya, komoditas apa yang ditanam, itu tergantung ordonansi. Selain itu, tanah-tanah yang tak memiliki hak miliki mutlak (eigendom) dikuasai oleh pemerintah.
Setelah kemerdekaan Indonesia, tanah masih menjadi persengketaan. Masalah-masalah baru bermunculan. Pertama, masih adanya tanah yang dimiliki oleh Belanda di negeri ini. Kedua, belum ada regulasi yang mengatur mengenai tanah (ada sih sebenarnya, cuma regulasi bekas kolonial). Nah, atas dasar itu, pemerintah kala itu gencar untuk membuat regulasi mengenai tanah atau yang kemudian populer dengan istilah agraria (agraria di sini memiliki arti yang lebih luas dari tanah loh ya, bahkan air dan ruang angkasa itu termasuk ke dalam agraria). Selain masalah tersebut, perlunya payung hukum yang mengatur agraria dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah rakyat.
Pada 24 September 1960, ditetapkanlah UU RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang kemudian disingkat UUPA). UUPA memiliki 5 prinsip: (1) pembaruan hukum agraria kolonial menjadi hukum agraria nasional; (2) menjamin kepastian hukum; (3) penghapusan hak asing dan konsesi kolonial atas tanah Indonesia; (4) mengakhiri penghisapan feodal dan perombakkan struktur penguasaan tanah; dan (5) wujud implementasi pasal 33 UUD 1945. Dengan lahirnya UUPA ini, maka lahir pula istilah Reforma Agraria. Secara sederhana, reforma agraria adalah penataan kembali struktur pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah/wilayah, demi kepentingan petani kecil dan buruh tani.
Namun, pada masa orde baru, lama kelamaan istilah ini mulai padam. Padamnya istilah ini dapat kita lihat dari sudut pandang internasional dan nasional. Di tataran internasional, Food and Agriculture Organization (FAO), mengatakan bahwa reforma agraria tidak relevan. Mengapa? Alasan pertama, dikarenakan telah dicapainya technological breakthrough dalam produksi pangan, hal tersebut (katanya) mampu meningkatkan produktivitas dan surplus tanpa perlu adanya reforma agraria. Alasan kedua, munculnya model Marshall Plan. Model ini mampu memberikan paket pinjaman untuk membangun industri, khususnya industri pertanian. Nah, jika kita menilik masalah nasional, reforma agraria mulai hilang disebabkan kejadian G30S/PKI. Menurut anggapan rezim, istilah reforma agraria diasosiasikan dengan agenda politik dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Tahun 1990-an, reforma agraria ini mulai ramai kembali diperbincangkan. Namun, World Bank mengarahkan reforma agraria lebih kepada mekanisme pasar. Mengedepankan reforma agraria yang voluntary, bukan compulsory.
Baca juga: MOKAKU Berakhir, Mari Kita Memulai.
Dewasa ini, ngomongin agraria pasti pikiran kita langsung mengarah pada istilah petani. Namun, jangan bayangkan petani seperti di luar negeri loh ya: punya traktor, lahannya luas, memperkejakan orang lain untuk menggarap lahannya, dan tajir. Biasanya kalo petani yang begitu, di luar negeri sebutannya adalah farmer. Di Indonesia juga ada kok yang seperti itu, hanya saja tidak banyak. Kebanyakan ciri-ciri petani di Indonesia itu: melibatkan (hanya) keluarganya saja, dipengaruhi oleh pihak yang berkuasa (negara/swasta, yang berada di desa/perkotaan), dan masih memiliki budaya tradisional. Petani-petani ini lah yang menjamur di negara-negara berkembang. Dalam bahasa Inggris, petani model seperti ini disebut sebagai peasant.
Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, siapa yang ingin menjadi petani? Pasti jawabannya masih ragu-ragu, iya kan? Yang sudah mantap, pasti kebanyakan menjawab tidak. Ya tidak aneh sih, dengan banyaknya masalah yang dihadapi petani, siapa sih yang mau? Maka tidak aneh kalau Erick Habsbawn, seorang sejarawan Inggris, menyebut istilah “matinya petani”. Apakah iya akan terjadi?
Covid-19 dan Pengaruhnya Bagi Ekonomi Politik Dunia dan Indonesia
Beberapa waktu lalu, dunia mengalami chaos luar biasa. Hampir semua negara mengalami resesi ekonomi. Tak terkecuali negara Imperialis, Amerika Serikat (AS). Pada kuartal ke-II 2020, pertumbuhan ekonomi AS menurun sampai angka 32,9%. Artinya, AS mengalami resesi untuk pertama kalinya dalam 11 tahun terakhir. Alasannya, Covid-19 telah mengubah infrastruktur (ekonomi & politik) negara tersebut. Penyakit satu ini menyebkan anjloknya kegiatan ekspor dan impor, konsumsi rumah tangga yang merosot, dan turunnya investasi.
Kalau di negeri super power saja krisis, bagaimana Indonesia?
Ekonomi Indonesia sudah pasti dong memburuk juga. Dalam kuartal ke-II 2020, ekonomi Indonesia merosot 5,32%. Kalau cocokologi, ekonomi kita hampir mirip dengan tahun 1998-1999. Mantap kan? Jika bertanya alasannya, tentu tidak berbeda jauh dengan AS.
Selanjutnya, mari kita lihat statistik Covid-19 di Indonesia. Update terakhir pada 21-09-2020, yang telah positif ada pada angka 248.852, sembuh ada pada angka 180.797, dan meninggal ada pada angka 9.677. Ini bisa dibilang wow banget lah ya? Dibalik angka-angka tersebut, ada beragam problematik juga: suap menyuap agar mau jadi korban Covid-19 (agar dana dari pemerintah bisa turun ke Gugus Covid) dan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih tidak mengikuti Rapid Test atau SWAB Test. Alasannya? Mahal, Bro! Satu kali Rapid Test itu memerlukan biaya 150 ribu, itu pun banyak yang tidak akurat. Sedangkan, apabila ingin lebih akurat, mesti menjalani SWAB Test yang harganya ada di kisaran 1,5 juta rupiah.
Saya yakin, negara pasti dilematis dengan pilihan-pilihan yang ada. Negara harus memilih salah satu antara menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan manusia. Ketika memilih menyelematkan ekonomi, itu artinya negara harus berterima kalau Covid-19 akan berkembang sangat pesat (seperti di AS). Ketika memilih menyelamatkan manusia, itu artinya negara harus siap menerima resesi yang lebih dahsyat. Dilematis bukan?
Negara berada di posisi abu-abu, sehingga kebijakannya pun demikian. Di daerah Jabodetabek, pemerintah setempat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maksimum semenjak 14 September (ada desas desus hal tersebut ada sangkutpautnya dengan agenda politik yaitu pemilihan pemimpin daerah). Sedangkan, di daerah-daerah lainnya diterapkan protokol Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Di Jawa Barat sendiri, protokol AKB telah dituangkan dalam bentuk regulasi Pergub No. 60 Tahun 2020.
Pertanyaan besarnya, bisakah hal tersebut menangani masalah Covid-19 di Indonesia? Biar waktu yang menjawab.
Baca juga: MOKAKU HARI KETIGA: PENGENALAN FAKULTAS, PENCERDASAN DINI, DAN PENUTUPAN.
Melihat Kondisi Tiga Elemen Rakyat: Kaum Tani, Kelas Buruh, dan Mahasiswa
Seperti yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, Covid-19 telah terbukti memengaruhi ekonomi dan politik Indonesia. Yang kemudian, itu akan berdampak pula pada elemen rakyat. Salah tiga elemes rakyat yang terdampak adalah kaum tani, kelas buruh, dan mahasiswa. Namun, tidak hanya sampai di situ masalahnya, meski belum disahkan, Omnibus Law sudah memberi dampak bagi elemen rakyat tersebut. Mari kita soroti kondisi dari masing-masing elemen rakyat.
Dimulai dengan kaum tani. Sebelum adanya Covid-19 dan wacana Omnibus Law, sektor agraria sudah memiliki masalah kritis. Setidaknya ada 5 masalah pokok: (1) ketimpangan struktur agraria; (2) konflik agraria struktural; (3) semakin masifnya kerusakan ekologi; (4) laju cepat alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian; dan (5) kemiskinan akibat struktur agraria.
Di kondisi sekarang, kaum tani semakin tersudutkan. Banyak dari kaum tani yang mengalami monopoli dan perampasan lahan, baik itu oleh negara maupun swasta. Jika kita main ke daerah Pangalengan, kita akan mendapati bahwa sekitar 17.000 hektar lahan telah dimonopoli. Beberapa perusahaan yang terlibat antara lain: Perum Perhutani, PTPN VIII, PT London Sumatra/Cukul Estate, PT Agro Jabar, serta PT Ultra Jaya & Trading Company. Itu baru di wilayah Pangalengan saja, belum lagi jika kita melihat tempat-tempat lainnya.
Kebijakan pembatasan sosial juga berdampak kepada petani. Dengan ditutupnya pasar-pasar kecil, harga komoditas yang dijual petani mulai anjlok. Ini terjadi sejak kebijakan pembatasan sosial ditetapkan pada triwulan pertama tahun ini. Sejak itu pula, petani mulai merugi. Mari kita lihat kondisi harga komoditas di Pangalengan. Sawi dan kol dari petani dihargai Rp. 1.000-1.500 perkilogram, sedangkan harga beli di pasar ada pada harga Rp. 1.500-7.500 perkilogram. Tomat, cabe rawit, cabe tewe, cabe keriting, cabe bendot, dan cabe tanjung dari petani dihargai Rp. 1.000-15.000 perkilogram, sedangkan harga beli di pasar ada pada harga Rp. 2.000-25.000 perkilogram. Umbi-umbian seperti wortel dan kentang dari petani dihargai Rp. 1.000-8.000 perkilogram, sedangkan harga beli di pasar ada pada harga Rp. 1.500-15.000 perkilogram. Belum lagi cuaca yang tidak memihak kepada petani (kekeringan) menyebabkan risiko gagal panen semakin membesar.
Apa yang terjadi ketika Omnibus Law disahkan? Tentu hal tersebut akan bersinggungan dan merugikan kaum tani. Pertama, Omnibus Law akan merevisi UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Impilikasinya adalah pemerolehan izin dalam mengonversi tanah pertanian pangan ke non-pangan akan lebih dimudahkan. Kedua, Omnibus Law akan mengubah UUPA yang telah mengatur Hak Guna Usaha (HGU). Pada UUPA, HGU hanya berlaku 25-35 tahun dan harus memenuhi syarat apabila ingin diperpanjang. Dalam Omnibus Law, HGU akan berlaku selama 90 tahun. Ini lebih lama daripada saat zaman kolonial, yaitu 75 tahun. Ketiga, Omnibus Law akan memperkuat posisi UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kepentingan umum di sini bisa saja diperluas menjadi kepentingan bisnis (pariwisata, pertambangan, kawasan ekonomi khusus (KEK)). Keempat, penghapusan ketentuan impor pangan. Kelima, pembentukkan “bank tanah” yang nantinya akan berfungsi sebagai rentenir di pedesaan.
Sekarang, mari kita beranjak ke sektor buruh. Perusahaan-perusaahan yang memperkerjakan kelas buruh merasakan dampak dari Covid-19. Di saat neraca ekonomi mulai goyah, buruhlah yang menjadi sasaran empuk. Maka tak aneh apabila kita melihat banyak buruh yang di PHK. Bukan hanya PHK, lebih banyak lagi buruh lainnya yang dirumahkan dan tidak mendapat upah. Misalnya di PT Kahatek, pada April-Mei, sekitar 11 ribu buruh dirumahkan. Rata-rata buruh tersebut adalah buruh kontrak.
Belum lagi hak yang semestinya didapatkan oleh buruh semakin sulit didapat. Misalnya dalam hal kesehatan, buruh semakin kesulitan dalam menggunakan BPJS dan Jamsostek. Hak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) juga belum sepenuhnya didapat. Misalnya, pada PT Natatex, buruh belum mendapatkan THR sebesar Rp. 500.000.
Baca juga: Filologi di Masa Kini
Masalah Omnibus Law jelas merugikan kelas buruh. Bukan hanya pada tataran regulasinya saja, dinamika politiknya pun mengalami masalah. Sepulang aksi penolakkan Omnibus Law, banyak buruh yang mendapatkan diskriminasi oleh buruh-buruh yang lain, tentu dengan permainan politik dari atasannya. Belum lagi, para buruh yang kritis tersebut mesti melakukan SWAB Test dan dirumahkan selama 14 hari tanpa upah.
Meskipun belum disahkan, beberapa perusahaan sudah menerapkan kebijakan Omnibus Law. Misalnya, sudah mulai menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan untuk upah buruh. Tentu menjadi realitas yang aneh ketika regulasinya belum ditetapkan, tetapi praktiknya sudah mengacu pada regulasi tersebut.
Dari sektor mahasiswa, tetap diberlakukannya sistem pembayaran perkuliahan di situasi sekarang menjadi masalah besar. Mayoritas dari orang tua mahasiswa terdampak ekonominya. Namun, kampus seolah lepas tangan terhadap masalah yang terjadi. Jika kita melihat hasil analisis Isola Menggugat, setidaknya ada 57% menginginkan penurunan UKT, 29% menginginkan pembebasan UKT sementara, 12% menginginkan perubahan kelompok UKT, dan 2% menginginkan pembayaran UKT secara berangsur.
Padahal, jika melihat kebijakan Kemdikbud, perkuliahan semester ini diarakan kepada metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Lantas pertanyaannya, ketika kita tidak ke kampus dan mendapat fasilitas kampus, kemanakah UKT kita? Nampaknya, hal tersebut belum dijawab oleh pihak kampus. Dalam proses belajar mengajar, PJJ juga memiliki kendala. Misalnya, masalah alat komunikasi dan sinyal. Tidak semua mahasiswa memiliki alat komunikasi yang dapat menunjang PJJ. Begitupun sinyal, banyak dari mahasiswa yang berada di daerah pedesaan dan sulit mengakses internet. Dalam masalah ini, kampus tidak peduli.
Di beberapa kampus, ada pun pemberian bantuan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Setidaknya ada dua jenis bantuan berdasarkan sumbernya: Kemdikbud dan kampus. Di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kemdikbud memberikan bantuan sebanyak 2.577 kepada mahasiswa. Namun faktanya, hanya 1.742 mahasiswa yang mendapatkan bantuan tersebut. Hal itu sangat disayangkan apabila melihat masih banyaknya yang memerlukan bantuan untuk mengakses pendidikan tinggi. Begitu pula dengan pemberian bantuan yang diberikan oleh kampus. Tidak trasnparannya kampus mengenai bantuan yang diberikan menjadi masalah. Belum lagi, tidak tepatnya sasaran penerima bantuan. Syarat yang ribet dan adanya kemungkinan yang besar kalau pewawancara (Pembimbing Akademik) berlaku subjektif menjadi masalah lain.
Mahasiswa, baik sadar maupun tidak, akan ikut terdampak Omnibus Law. Apalagi dengan diberlakukannya kebijakan Kampus Merdeka. Beberapa kampus berlabel PTNBH sudah mulai menerapkan kebijakan ini (walaupun beberapa kampus masih pada tataran uji coba). Nantinya, mahasiswa akan menjalani proses magang setidaknya satu tahun. Perusahaan akan sangat diuntungkan dengan hadirnya mahasiswa. Sebab, mereka akan mendapatkan tenaga kerja (jika tidak mau disebut buruh) segar dengan upah murah (bahkan bisa jadi gratis) dengan dalih pembelajaran. Hal tersebut, akan semakin melanggengkan liberalisasi dan komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia.
Rencana Taktis dan Strategis Untuk Kesejahteraan Nasional
Setidaknya, ada dua rencana strategis yang ditawarkan ketika berbicara penyelesaian masalah kaum tani, buruh, dan mahasiswa: Reforma Agraria dan Industri Nasional. Namun, dalam konteks ini, mari kita berfokus pada reforma agraria.
Reforma Agraria yang dimaksud di sini bukanlah reforma agraria yang diusung oleh Jokowi dalam Nawacita-nya. Reforma Agraria di sini lebih dari sekadar pembagian sertifikat tanah!
Baca juga: Waktu Bergerak, Kondisi Berjarak Kita Berhenti Berjalan
Dalam studi agraria, reforma agraria terbagi dalam 3 jenis berdasarkan ideologi: Reforma Agraria (neo) Populis, Reforma Agraria Kapitalis, dan Reforma Agraria Sosialis. Reforma Agraria (neo) Populis diprakarsai oleh Chayanov. Reforma Agraria ini lebih berfokus kepada Family Farm. Artinya, pemilik lahan menjalani produksi dan konsumsi sekaligus. Otomatis tidak ada insentif di dalamnya. Reforma Agraria Kapitalis diusung oleh Locke. Menurutnya, tanah adalah kepemilikan pribadi dan harus selalu berfokus pada profit. Sistem ini nantinya akan semakin mengembangkan tuan tanah dan memperbanyak buruh tani. Terakhir, Reforma Agraria Sosialis yang diusung oleh Marx. Baginya, kepemilikan tanah merupakan milik kolektif. Bukan hanya kepemilikannya saja, tetapi pengerjaan lahan pun mesti dilakukan secara kolektif.
Jika kita melihat Reforma Agraria yang dijalankan oleh Jokowi, itu hanya menyelesaikan masalah legalisasi aset tanpa menyelesaikan masalah yang telah mengakar. Bahkan, sertifikat ini juga bisa jadi menambah masalah baru bagi kaum tani di Indonesia. Kita sama-sama tahu, masalah transfer lahan bisa jadi timbul akibat dari kebijakan ini. Transfer lahan dapat terjadi, baik secara sukarela maupun paksa.
Ketika pemerintah hari ini tidak memberikan peran apapun dalam produksi pertanian, petani kecil yang tidak memiliki modal, tidak bisa menjalankan produksi. Mereka tidak mampu membeli bibit, alat, pupuk, obat, dsb. Sertifikat tanah hanya akan mempermudah tranfer tanah secara sukarela kepada negara ataupun swasta. Belum lagi jika melihat banyaknya sengketa tanah hari ini. Sekalipun memiliki sertifikat, kaki tangan pemerintah (aparatur negara), asal mendapat suruhan dari atasan, akan mengintervensi si pemilik tanah agar menjual tanahnya (dengan embel-embel bahwa tanah tersebut untuk kepentingan bersama). Inilah yang dimaksud transfer tanah secara paksa. Legalitas aset ini juga bisa membantu pemerintah dalam melihat tanah kosong yang belum terdaftar. Secara otomatis, tanah tersebut akan dikuasai oleh negara.
Oleh karenanya, reforma agraria di sini merupakan reforma agraria yang sejati. Reforma Agraria yang bukan hanya pada land reform (tata kuasa dan tata guna), tetapi pada access reform. Jika pemerintah hanya berfokus pada tata kuasa, sesungguhnya itu hanya sebagian kecil dari reforma agraria. Tata kuasa mengharuskan tanah sepenuhnya dikelola oleh rakyat. Sedangkan, tata guna akan berhubungan dengan keseimbangan ekologis. Bagaimana sebuah tanah mesti dilengkapi dengan fasilitas umum, ruang terbuka hijau, dsb. Setelah kedua hal tersebut terpenuhi, barulah kita berfokus pada access reform. Di sini kita mengatur kembali mulai dari produksi, distribusi, sampai kepada konsumen. Ini berarti mencakup aspek-aspek seperti pengairan, pendidikan, penyuluhan, pemasaran, dsb.
Namun, nampaknya reforma agraria akan sulit tercapai apabila masih ada kepentingan bisnis bersangkut di kepentingan politik. Kita dapat melihat banyaknya pengusaha yang beralih profesi atau seminimalnya berafiliasi dengan partai politik. Sehingga, kepentingan bisnis mereka akan tertuang di kebijakan-kebijakan politik. Namun, selain lewat jalur kebijakan, reforma agraria juga bisa dituntut secara paksa. Hanya saja perlu ada pencerdasan politik terhadap kaum tani. Seluruh elemen masyarakat mesti berjuang bersama kaum tani. Sebab reforma agraria ini berawal dari sektor pertanian itu sendiri.
Adapun cara taktis untuk mengatasi masalah kesejahteraan pangan ini. Salah satunya adalah dengan pembangunan koperasi. Koperasi yang dimaksud di sini mestilah koperasi yang berasaskan kolektif. Artinya, mesti terlepas dari prinsip-prinsip kapitalisme. Mengapa koperasi dipilih, berikut adalah alasannya:
- Koperasi adalah people based association. Oleh karenya, koperasi dapat melakukan negoisasi harga yang adil, pembagian resiko yang jelas, dan bisa saling bertukar informasi, pengetahuan, dan keterampilan.
- Besarnya modal. Dengan kerja-kerja kolektif, modal yang terkumpul untuk menjalankan produksi akan terbantu. Modal yang dimaksud di sini adalah sebagai pembantu, bukan penentu. Misalnya, dalam penggunaan alat produksi, petani dapat saling bertukar alat produksi.
- Meningkatkan skala ekonomi. Hal tersebut dikarenakan adanya kerja sama antar petani. Ketika petani (sekalipun petani kecil) bersatu, maka mereka bisa memiliki modal produksi yang sama dengan petani besar. Dalam situasi konkret, kerja sama ini bisa kita lihat dalam pembelian alat produksi bersama-sama.
- Menjaga kualitas hidup. Dengan bekerja kolektif, artinya akan ada pembagian tanggung jawab, baik dalam segi produksi maupun distribusi. Ini akan memudahkan petani untuk menghemat waktunya dan dapat digunakan untuk kepentingan lain (keluarga, pendidikan, dsb).
Ini aka semakin dapat diwujudkan apabila melihat kondisi massa tani yang banyak dan tertata serta terkoordinasi dengan baik.
Epilog
Kaum tani dan kelas buruh memiliki andil besar dalam terjadinya revolusi sebuah tatanan yang sudah mapan. Oleh karenanya, tidak aneh apabila dua kelompok ini menjadi pemimpin dari gerakan revolusioner hari ini. Dimana peran kita, selaku mahasiswa, selaku borjuasi kecil? Tentu kita mesti menyokong gerakan tani dan gerakan buruh agar dapat mewujudkan reforma agraria (dan tentu Industri Nasional).
Meskipun masih banyak yang belum selesai dibahas mengenai reforma agraria, misalnya dalam arah transasksi, apakah reforma agraria yang akan dipilih itu colectivist reform atau redistributive reform? Selanjutnya, akan memilih model yang seperti apa (dalam penentuan batas maksimum dan minimum)? Apakah batas luas maksimum dan minimum ditetapkan? Apakah batas maksimum ditetapkan dan batas minimum dibebaskan? Apakah batas maksimum dan minimum dibebaskan? Tentulah, sebelum bergerak, kita harus menentukan dulu mana yang akan kita pilih.
Menuju Hari Tani Nasional ke-60, nampaknya tidak akan ada yang turun ke jalan (melihat situasi nasional, regional, kaum tani, dan kelas buruh). Itu artinya kita mesti mencari bentuk lain dalam memperingatinya. Melakukan pencerdasan mengenai kondisi buruh, tani, mahasiswa dapat menjadi pilihan. Atau, membuat propaganda-propaganda yang disebarkan melalui media sosial, nampaknya itu juga bukan menjadi solusi yang buruk. Namun, yang terpenting adalah tetap berdiskusi langsung bersama buruh dan tani, khususnya membahas mengenai apa yang bisa kita lakukan hari ini dan nanti. Jangan sampai gerakan mahasiswa terpisah dengan gerakan tani dan buruh.
Selamat Hari Tani Nasional!
“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan mengaggap
dirinya terlalu tingi dan pintar untuk melebur dengan
masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan
memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik
pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.”
Madilog, Tan Malaka
*Paper ini disampaikan pada diskusi “Menuju Hari Tani Nasional” yang diselenggarakan oleh UKSK UPI pada tanggal 22 September 2020.
Baca juga: SEDIKIT PENDAPAT TENTANG PROBLEMATIK UKT
Penulis: Tofan Aditya